Opini
Membaca Alarm Krisis Kohesi Sosial di Kota Makassar
Di balik berbagai peristiwa itu, tersimpan pesan penting bahwa struktur sosial di tingkat akar rumput sedang rapuh.
Oleh: Asri Tadda (Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan)
TRIBUN-TIMUR.COM - Krisis kohesi sosial kota.
Dalam beberapa waktu terakhir, kita menyaksikan peningkatan kasus tawuran antarkelompok remaja, bentrokan warga di sejumlah titik, hingga maraknya aksi kriminalitas jalanan yang terjadi hampir setiap pekan.
Fenomena ini bukan lagi insiden terpisah, tetapi sudah menjadi pola sosial yang mengkhawatirkan.
Di balik berbagai peristiwa itu, tersimpan pesan penting bahwa struktur sosial di tingkat akar rumput sedang rapuh.
Rasa kebersamaan, saling percaya, dan tanggung jawab kolektif yang dulu menjadi ciri khas masyarakat Kota Daeng, perlahan memudar. Padahal nilai-nilai itulah yang selama ini membuat Makassar kuat, hangat, dan khas sebuah kota dengan identitas sosial yang kohesif.
Bagi saya, situasi ini tidak cukup dijelaskan dengan dalih kenakalan remaja atau lemahnya penegakan hukum. Akar persoalannya jauh lebih dalam.
Kita sedang menghadapi krisis sosial, krisis dalam jaringan kehidupan bersama yang selama ini menjadi perekat antarwarga kota.
Ketika ikatan sosial itu retak, kota kehilangan daya lentingnya dalam menghadapi tekanan ekonomi, laju urbanisasi, hingga gempuran budaya digital yang serba instan.
Inilah yang seharusnya terbaca sebagai alarm sosial bagi para pemimpin kota. Sebuah peringatan dini bahwa tata kelola kota tidak bisa lagi hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik dan layanan publik semata.
Mengelola kota dengan lebih dari satu juta penduduk memerlukan kecerdasan sosial, kepekaan budaya, dan kemampuan melakukan rekayasa sosial (social engineering) yang tepat.
Kepemimpinan kota yang efektif bukan hanya soal administratif dan elektoral, tetapi juga soal bagaimana menata ulang struktur sosial agar tetap kokoh di tengah perubahan zaman.
Demokrasi Mikro dan Risiko Sosial
Salah satu kebijakan yang perlu dikaji secara kritis adalah rencana penerapan pemilihan langsung ketua RT dan RW dengan model one man one vote (OMOV).
Sekilas, kebijakan ini tampak demokratis karena memberi kesempatan bagi warga untuk memilih langsung pemimpinnya di tingkat paling bawah. Namun dalam praktiknya, kebijakan semacam ini bisa menimbulkan persoalan sosial yang tidak kecil.
Dalam masyarakat homogen yang memiliki jaringan sosial kuat, sistem OMOV mungkin bisa berjalan baik.
Tetapi dalam konteks masyarakat urban seperti Makassar yang semakin heterogen, di mana hubungan antarwarga mulai renggang dan individualisme menguat, sistem itu justru berpotensi menimbulkan rivalitas baru di lingkungan terkecil masyarakat.
RT dan RW yang seharusnya menjadi simpul sosial dan ruang gotong royong bisa berubah menjadi arena kontestasi politik mini. Solidaritas sosial bisa terpecah oleh polarisasi dukungan, dan hubungan bertetangga yang semula harmonis bisa terganggu oleh sisa-sisa persaingan politik tingkat lokal.
Inilah yang saya maksud dengan risiko sosial dari demokrasi mikro yang tidak disiapkan dengan matang.
Karena itu, kebijakan semacam ini perlu dirancang dengan sangat hati-hati. Demokrasi di tingkat mikro tetap harus menjamin kohesi sosial, bukan justru menggerusnya.
Membangun Ulang Kohesi Sosial Kota
Makassar membutuhkan strategi yang melampaui pendekatan penertiban dan keamanan. Tawuran dan kekerasan jalanan tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah patroli atau operasi aparat.
Yang dibutuhkan adalah rekayasa sosial yang cerdas, halus, dan berjangka panjang—strategi yang berfokus pada pemulihan fungsi sosial komunitas dan penguatan ruang interaksi warga.
Kita perlu menghidupkan kembali ruang-ruang sosial yang selama ini hilang. Ruang olahraga komunitas, taman publik, kegiatan lintas RW, hingga pusat aktivitas pemuda bisa menjadi wadah yang memulihkan semangat kebersamaan.
Pemerintah kota perlu hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator terbentuknya ruang sosial baru yang sehat dan inklusif.
Dalam teori sosiologi klasik, Émile Durkheim menyebut kohesi sosial sebagai lem sosial (social glue) yang menjaga masyarakat tetap utuh di tengah perbedaan.
Ketika integrasi sosial melemah, masyarakat akan masuk ke dalam kondisi anomie keadaan di mana norma-norma kehilangan kekuatan untuk mengatur perilaku individu.
Gejala anomie ini sudah tampak jelas di beberapa lingkungan urban Makassar. Kita melihat anak-anak muda yang kehilangan orientasi sosial, melemahnya nilai kebersamaan, dan munculnya rivalitas antarwilayah yang memicu konflik kecil. Maka, pembangunan kohesi sosial menjadi keharusan, bukan pilihan.
Selain memperkuat ruang interaksi, pemerintah juga perlu mengadopsi pendekatan sosio-edukatif. Sekolah, lembaga keagamaan, komunitas warga, dan organisasi lokal bisa menjadi bagian dari sistem pencegahan sosial yang terintegrasi.
Pemerintah kota dapat bekerja sama dengan akademisi, pekerja sosial, dan tokoh masyarakat untuk mengembangkan program literasi sosial dan pendampingan keluarga yang berkelanjutan.
Kota sebesar Makassar tidak dapat dikelola hanya dengan pendekatan birokratis dan administratif. Ia membutuhkan sentuhan sosial yang empatik, kepemimpinan yang memahami denyut komunitas, serta kebijakan publik yang berpihak pada penguatan jaringan sosial warga.
Pemimpin kota di masa kini dan mendatang dituntut untuk memiliki visi sosial yang kuat.
Mereka tidak cukup hanya piawai membangun jalan, stadion, atau gedung megah. Yang lebih penting adalah kemampuan membangun kembali jalinan sosial antarwarga menyulam ulang rasa kebersamaan yang mulai koyak oleh dinamika politik dan ekonomi kota.
Dalam konteks ini, kemampuan melakukan social engineering menjadi kunci utama.
Pemimpin yang mampu memahami perilaku sosial masyarakat dan merancang interaksi sosial yang produktif akan jauh lebih berhasil menjaga stabilitas dan harmoni kota dibanding mereka yang hanya mengandalkan kekuasaan politik.
Kebijakan publik yang terlihat demokratis di permukaan harus selalu diuji dampak sosialnya di lapangan.
Jangan sampai niat baik untuk memperluas partisipasi justru menimbulkan perpecahan baru di tengah masyarakat.
Pemilihan RT/RW langsung, misalnya, bisa menjadi ladang konflik laten jika tidak diatur dengan mekanisme sosial yang bijak.
Pemerintah perlu berani meninjau ulang kebijakan apa pun yang berpotensi mengacaukan struktur sosial masyarakat.
Pembangunan kota yang berkelanjutan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga dari seberapa kuat masyarakatnya saling percaya dan saling peduli.
Makassar bukan sekadar kota padat dan dinamis. Ia adalah ruang sosial yang hidup, dengan sejarah panjang solidaritas, gotong royong, dan kebanggaan kolektif. Nilai-nilai inilah yang perlu kita revitalisasi bersama.
Alarm krisis kohesi sosial yang kini berbunyi harus menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menata ulang arah pembangunan kota.
Makassar harus bergerak menuju keseimbangan baru—antara kemajuan fisik dan keutuhan sosial, antara pertumbuhan ekonomi dan ketenangan batin warganya.
Karena pada akhirnya, kekuatan sejati sebuah kota tidak terletak pada megahnya gedung atau jalan-jalan yang mulus, melainkan pada kuatnya rasa saling percaya di antara penghuninya. Dan di situlah, kohesi sosial menemukan maknanya yang paling dalam. (*)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/2025-10-16-Asri-Tadda.jpg)




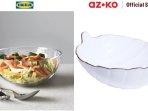
















Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.