Opini
Bulu Alauna Tempe dan Kitab Kuning: Orkestra Santri dari Danau Tempe untuk Dunia
Hari pembukaan Musabaqah Qiraatul Kutub Internasional di As’adiyah terasa seperti samudera kecil yang bernafas.
Muhamad Majdy Amiruddin
Dosen IAIN Parepare
HARI pembukaan Musabaqah Qiraatul Kutub Internasional di As’adiyah terasa seperti samudera kecil yang bernafas.
Suara biola pertama melengking lirih, seperti riak air yang mulai bergelombang.
Terompet menyusul, meniupkan gema bagai angin pagi yang melintasi rawa dan danau.
Di belakangnya, cello menebalkan nada, menghadirkan kedalaman seperti dasar air yang menyimpan rahasia.
Lalu tiba giliran gendrang Bugis memukul ritme: dumm tak, dumm tak, denyutnya menyatu dengan detak jantung para hadirin.
Kecapi petik menjerit halus, seakan menyulam suara perahu yang didayung perlahan.
Suling bambu melayang di udara, mengikat semua nada menjadi satu jalinan.
Baca juga: Deretan Tokoh Hadir di Pembukaan MQK Nasional dan Internasional Wajo
Di titik itu, harmoni tak lagi bisa dipisahkan: modern dan tradisi, darat dan danau, masa kini dan masa lalu.
Tepuk tangan bergulung seperti ombak, namun di balik gemuruh itu masih terdengar lirih doa yang keluar dari bibir santri.
Dan orkestra itu mengawali segalanya dengan satu lagu: Bulu Alauna Tempe—nyanyian danau yang kini berpadu dengan nada dunia.
Bulu Alauna Tempe bukan hanya nada; ia adalah tafsir rakyat yang mengeja alam dengan bahasa metafora.
Syairnya menuturkan tentang gunung, air, dan para nelayan, menyulam pesan kepemimpinan, kesabaran, dan amanah di antara bait-baitnya.
Ketika dinyanyikan, lagu itu seperti menerjemahkan permukaan danau menjadi huruf-huruf yang bisa dibaca oleh generasi muda.
Nada-nadanya mengingatkan bahwa pemimpin harus tegak seperti gunung, mengayomi seperti pohon, dan tidak tenggelam oleh arus kekuasaan.
Lagu itu juga memperingatkan agar kekuasaan tidak memakan akar, karena benang kusut dan rakit yang tak seimbang bisa menenggelamkan siapa saja.
Dalam pembukaan MQK, lantunan lagu itu menjadi jembatan antara riak lokal dan gema internasional.
Dari situ kita paham: membaca kitab dan menyanyikan danau adalah dua ritual yang saling memperkaya.
Jika bait-bait Bulu Alauna Tempe diterjemahkan ke dalam bahasa hari ini, ia akan berbicara tentang limpahan rezeki yang tak pernah kering, tentang danau yang bukan hanya air tetapi rahim peradaban.
Inilah tafsir hidup masyarakat yang menggantungkan diri pada perahu, jala, dan ikan.
Dalam suara santri, makna itu seperti lahir kembali: bahwa kitab bisa dibaca dari lembaran kertas, tapi juga dari gelombang air dan riak-riak danau.
Kitab bisa dihafal lewat huruf Arab gundul, tapi juga lewat syair Bugis yang disulam dalam ingatan.
Danau Tempe sejak lama adalah nadi ekonomi Sulawesi Selatan. Nelayan menjaring ikan, pedagang perempuan menjual hasil tangkapan di pasar, dan rumah-rumah terapung menari di atas air.
Para peneliti dunia menegaskan hal itu.
Misalnya, Christian Pelras (1996, The Bugis) menulis bahwa Danau Tempe adalah contoh adaptasi ekologis luar biasa masyarakat Bugis: rumah berpindah mengikuti arus, ekonomi berdenyut dari ikan, dan budaya lahir dari air.
Begitu pula catatan VOC abad ke-17 lewat laporan Cornelis Speelman, yang menyebut kawasan rawa luas tempat rakyat hidup dari perairan, meski nama “Danau Tempe” belum dipakai.
Semua ini menunjukkan bahwa danau itu bukan sekadar bentangan air, melainkan teks besar yang selalu bisa dibaca ulang. Kerajaan-kerajaan di sekitar danau juga lahir dari denyut air ini.
Ajattapareng—aliansi kerajaan Sidrap, Suppa, Rappang, Sawitto—berdiri tak jauh darinya. Soppeng dan Bone menjalin persekutuan sekaligus persaingan.
Wajo, yang bernaung di tepi Danau Tempe, tampil dengan identitas egaliter: rakyat punya suara, pemimpin hanyalah pelaksana, bukan penguasa mutlak. A.A. Cense (1931) dalam kajiannya tentang Lontara Wajo menegaskan bagaimana struktur sosial Wajo memberi ruang musyawarah yang lebih luas ketimbang kerajaan lain.
Danau Tempe bukan hanya sumber pangan, melainkan metafora bagi demokrasi ala Bugis—airnya menampung banyak ikan, banyak perahu, banyak suara. R.A. Kern (1939) menyebut bagaimana kerajaan-kerajaan Bugis memadukan adat dan syariat, sehingga ajaran Islam tidak hadir sebagai benturan, melainkan sebagai sulaman baru di atas kain lama.
Masjid-masjid di tepi danau berdiri berdampingan dengan rumah adat, dan para saudagar membawa kitab bersama dagangan mereka.
Seperti air yang menyusup ke celah tanah, Islam di Wajo meresap ke dalam denyut budaya, hingga lahirlah generasi ulama dan santri yang menggabungkan ilmu, adat, dan etos kerja.
Puncak institusionalisasi ilmu itu lahir pada 1930, ketika Anregurutta Muhammad As’ad (1907–1952) kembali dari Makkah.
Lahir di tanah suci, belajar di Madrasah al-Falah, bahkan sempat menjadi sekretaris Syekh Ahmad Sanusi, beliau membawa semangat tajdid.
Di Sengkang, beliau mendirikan Madrasah Arabiyah Islamiyah—yang kelak dikenal sebagai Pesantren As’adiyah.
Dari danau ia belajar tentang air kehidupan, dari Makkah ia membawa sanad ilmu, dan dari keduanya lahir lembaga yang hingga kini jadi rahim keilmuan Sulawesi. As’adiyah kemudian menjadi mercusuar.
Dari sinilah lahir ribuan ulama, dai, dan guru. Mereka menyebar ke timur Nusantara—Maluku, Nusa Tenggara, Papua, bahkan Malaysia.
Salah satu yang paling berpengaruh adalah Gurutta Abdurrahman Ambo Dalle, murid kesayangan Gurutta As’ad, yang mendirikan Darud Dakwah wal Irsyad (DDI).
Baca juga: Prof Ismail Rektor IAIN Langsa Hadiri MQK di Wajo: Semoga As’adiyah Terus Lahirkan Ulama
Jika As’adiyah adalah mata air, maka DDI adalah sungai yang mengalirkan ilmunya ke seluruh kawasan timur Nusantara.
Inilah bukti bahwa air dan ilmu saling bertaut: danau memberi kehidupan, pesantren memberi pengetahuan.
Sejak awal, As’adiyah juga tidak terisolasi. KH. As’ad lahir di Makkah, berguru pada ulama Haramain, dan mewarisi jejaring ulama Nusantara di Masjidil Haram.
Di sana, ia bertemu dengan murid-murid Syekh Ahmad Khatib Minangkabau—guru yang juga mendidik KH. Hasyim Asy’ari, pendiri NU. Maka, sanad As’adiyah seirama dengan sanad pesantren Jawa.
Hubungan itu seperti jembatan panjang dari Tebuireng ke Sengkang, dari Lirboyo ke Danau Tempe. Jembatan itu bukan dari besi atau beton, melainkan dari kitab kuning, doa, dan persaudaraan ulama.
Ketika Musabaqah Qiraatul Kutub Internasional kini digelar di As’adiyah, jembatan itu tampak nyata.
MQK bukan sekadar lomba baca kitab, melainkan peristiwa simbolik: kitab kuning dibaca dari tepian danau, bukan hanya dari tanah Jawa. Tradisi baca kitab ternyata tidak pernah tunggal, ia tumbuh dalam pluralitas lokal.
Selama ini kita mengenal Tebuireng, Krapyak, Sidogiri, Lirboyo. Kini Sengkang, lewat As’adiyah, menunjukkan bahwa riak Danau Tempe pun bisa bergema hingga ke samudera dunia.
Maka, apa yang terjadi hari ini adalah perputaran sejarah.
Dari Danau Tempe yang airnya menghidupi, dari Wajo yang egaliter, dari Gurutta As’ad yang visioner, dunia diajak kembali membaca: Islam Nusantara bukan hanya Jawa, tapi juga Bugis.
Bulu Alauna Tempe yang dinyanyikan santri pada pembukaan MQK adalah terjemahan puitis atas sejarah itu.
Ia menjahit air dan kitab, budaya dan agama, ekonomi dan ilmu, dalam satu tarikan napas.
Musabaqah Qiraatul Kutub yang selama ini lekat dengan tradisi Jawa kini meluas dan memperkaya koor Nusantara dengan suara Bugis; ia adalah dialog antarpulau, bukan kompetisi klaim kultural.
Di panggung internasional, santri Bugis kini mengeja kitab dengan aksen sendiri, namun dengan kelenturan bahasa universal yang dipahami khalayak global.
Baca juga: Buka MQK Internasional di Wajo, Menag Nasaruddin Umar: Pesantren Poros Perdamaian
Peristiwa itu menandai bahwa Islam Nusantara adalah mozaik, dan As’adiyah adalah salah satu batu permatanya.
Dengan MQK, kitab-kitab kuning tidak lagi terbaca dalam lingkup sempit, tetapi menjadi wacana antarbangsa.
Dari riak Danau Tempe, gelombang ilmu kini melaju ke samudera dunia. Inilah saat di mana lokal dan global bertemu dalam satu pelabuhan ilmu.
Seperti sungai yang bermuara ke laut, demikian pula ilmu yang berawal dari tepian Danau Tempe harus mengalir sampai ke horizon yang lebih luas.
Lagu Bulu Alauna Tempe yang mengawali MQK adalah pengingat bahwa akar budaya mesti dirawat agar cabang ilmu tidak patah.
Penelitian-penelitian empiris tentang Danau Tempe menggarisbawahi tanggung jawab kolektif: ilmu agama dan ilmu alam harus berjalan beriringan.
MQK Internasional di As’adiyah bukan hanya momen kebanggaan, tetapi juga awal kolaborasi riset yang mengundang dunia untuk belajar dan menjaga Danau Tempe.
Semoga santri-santri yang mengeja kitab di tepian itu kelak menjadi peneliti, pengelola, dan pemimpin yang membawa warisan Bugis ke panggung dunia dengan penuh tanggung jawab.
Dari riak kecil hingga gelombang besar, kita belajar satu pelajaran lama: ilmu yang baik adalah ilmu yang merawat.(*)

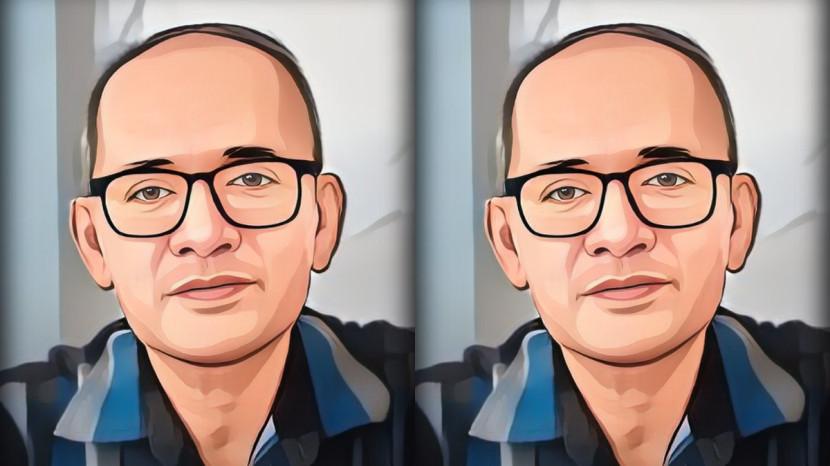


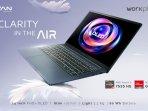

















Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.