Opini
Ulama yang Digantikan Mesin: Krisis Otoritas dan Nalar Islam di Era AI
Pertanyaan keagamaan yang dulu dijawab dengan musyawarah, renungan, dan keilmuan kini bisa dijawab oleh mesin dalam hitungan detik.
Oleh: Prof Hannani
Rektor IAIN Parepare
TRIBUN-TIMUR.COM - Umat Islam kini hidup di zaman ketika fatwa tak lagi lahir dari ruang kajian, tetapi dari pusat data.
Pertanyaan keagamaan yang dulu dijawab dengan musyawarah, renungan, dan keilmuan kini bisa dijawab oleh mesin dalam hitungan detik.
Cukup ketik: “Apakah investasi kripto halal?” dan algoritma segera menampilkan fatwa yang rapi, lengkap dengan dalil dan referensi mazhab.
Fenomena “fatwa digital” ini tampak mengagumkan, tetapi di balik efisiensi algoritma tersimpan kegelisahan besar: apakah umat sedang beralih dari budaya ijtihad menuju budaya instan?
Apakah mesin bisa menggantikan kedalaman nalar dan kehangatan nurani yang selama ini menjadi ruh hukum Islam?
Dari Ijtihad ke Algoritma
Dalam sejarah Islam, hukum tidak pernah statis. Ia hidup dari ijtihad proses pencurahan akal dan jiwa seorang ulama untuk memahami kehendak Tuhan di balik teks.
Ulama seperti Imam Syafi’i, Al-Ghazali, atau Ibn Taymiyyah bukan sekadar menghafal dalil, tetapi membaca realitas.
Kini, peran itu mulai diambil alih oleh Artificial Intelligence (AI). Aplikasi seperti “AI Fatwa Assistant” yang dikembangkan di Mesir, Uni Emirat Arab, dan Malaysia mampu mengolah ribuan teks fiqh dari empat mazhab besar untuk menjawab persoalan hukum.
Dar al-Ifta Mesir bahkan mengumumkan proyek AI mufti untuk “memperluas akses umat terhadap bimbingan syariah.”
Namun, seperti diingatkan pakar hukum Islam kontemporer Abdallah bin Bayyah, hukum Islam bukan hanya kumpulan data normatif, melainkan hikmah yang lahir dari kesadaran spiritual.
“Tidak cukup memahami ayat, seseorang harus memahami manusia,” ujarnya dalam sebuah simposium fikih di Abu Dhabi (2023).
Budaya Instan dan Krisis Refleksi
Secara sosiologis, penerimaan cepat terhadap fatwa AI bisa dijelaskan melalui Teori Difusi Inovasi Everett Rogers: masyarakat cenderung mengadopsi teknologi yang menawarkan relative advantage lebih cepat, lebih mudah, lebih efisien.
Namun, dalam konteks keagamaan, kecepatan sering berbanding terbalik dengan kedalaman.(Dryden-Palmer et al., 2020)
Fenomena ini terlihat dalam riset M. Billah yang menilai model NLP seperti ChatGPT dan Google Bard belum dapat menggantikan mufti manusia.(Billah et al., 2023)
Alasannya sederhana: algoritma tidak memahami maqasid al-syari‘ah, tujuan moral di balik teks hukum.
Umat pun perlahan beralih dari proses mencari kebenaran menuju konsumsi jawaban.
Budaya refleksi digantikan budaya reaksi. Fenomena ini mengarah pada apa yang disebut para psikolog sebagai cognitive offloading kecenderungan otak menyerahkan beban berpikir pada mesin.(Skulmowski, 2023)
Dalam konteks keagamaan, ini adalah brain rot spiritual: hilangnya kemampuan bernalar dan menimbang.
Krisis Otoritas Ulama
Lebih dari sekadar soal kecepatan, fatwa AI mengguncang tatanan otoritas dalam hukum Islam.
Selama berabad-abad, otoritas ulama dibangun di atas sanad keilmuan—rantai ilmu dan moralitas yang menghubungkan generasi ke generasi.
Kini, otoritas itu perlahan bergeser ke layar. KH Cholil Nafis dari MUI menegaskan bahwa “kecerdasan buatan tak bisa menggantikan ulama karena tidak memiliki kesadaran moral.”
Namun, bagi generasi digital, kredibilitas sering diukur dari kecepatan, bukan keilmuan.
Jika dulu umat bertanya pada kiai karena percaya pada kesalehan dan ilmunya, kini umat bertanya pada aplikasi karena percaya pada algoritmanya.
Pertanyaannya: kepada siapa ketaatan diarahkan kepada manusia yang beriman, atau mesin yang efisien?
Lebih jauh, AI belajar dari data daring yang belum tentu sahih. Jika dataset didominasi pandangan konservatif, algoritma akan memperkuat konservatisme; jika didominasi tafsir liberal, ia akan mereplikasi bias yang sama.
Seperti diingatkan Anne D. Trunk, AI mampu memberikan rekomendasi atau jawaban berbasis data.
Namun keputusan moral dan spiritual dalam agama melibatkan dimensi etika, empati, dan konteks budaya yang kompleks hal yang tidak dapat sepenuhnya dipahami atau diinternalisasi oleh algoritma.(Trunk et al., 2020)
Antara Efisiensi dan Empati
Kelemahan mendasar AI terletak pada absennya empati dan kesadaran. Dalam kasus hukum keluarga perceraian, warisan, atau hak asuh anak ulama sering menimbang dengan hati, bukan sekadar teks.
Ia membaca air mata, rasa malu, atau kesedihan—hal-hal yang tak dapat diterjemahkan ke dalam data.
AI mungkin benar secara teknis, tetapi bisa salah secara kemanusiaan.
Misalnya, dalam kasus perceraian karena kekerasan rumah tangga, AI bisa menyarankan “rujuk” karena dalil keutamaan rumah tangga.
Sementara ulama manusia akan mempertimbangkan keselamatan jiwa istri sebagai bagian dari maqasid al-syari‘ah: hifz al-nafs (menjaga nyawa).
Oleh karena itu, “AI harus dilihat sebagai alat bantu bagi ulama, bukan sebagai otoritas hukum itu sendiri. Tanpa bimbingan manusia, sistem AI berisiko menelurkan fatwa yang valid secara teks, tetapi salah secara konteks.
Menjaga Api Nalar
Kita tidak sedang menolak teknologi, melainkan mengingatkan batasnya. Islam tidak anti-modernitas; ia justru pernah memimpin ilmu dan sains karena menjunjung akal. Tetapi akal dalam Islam bukan alat mekanis, melainkan anugerah spiritual.
Sejarah menunjukkan, para ilmuwan Muslim klasik dari Al-Farabi hingga Ibn Rushd menyatukan iman dan rasio.
Mereka tidak membiarkan akal tunduk pada mesin. Karena itu, tantangan kita hari ini bukan bagaimana menciptakan “mufti digital”, melainkan bagaimana memastikan AI tetap menjadi khadim al-‘ilm (pelayan ilmu), bukan hakim al-din (penentu agama).
Dari Data Menuju Hikmah
Gelombang digitalisasi ini tak terelakkan. AI akan terus hadir dalam fatwa, tafsir, dan pendidikan agama.
Namun, tugas kita adalah memastikan bahwa kecepatan tidak membunuh kedalaman, dan data tidak menggantikan hikmah.
Fatwa sejatinya bukan produk statistik, tetapi hasil dialog antara teks, konteks, dan nurani. AI dapat membantu menelusuri dalil, tetapi hanya manusia yang mampu menimbang makna.
AI bisa mengutip ulama, tetapi tak bisa menanggung beban moral seorang mujtahid.
Kita boleh menggunakan algoritma, tetapi jangan menjadi algoritmik.
Sebab, ketika umat berhenti berpikir dan hanya menekan tombol, Islam kehilangan satu hal yang menjadikannya besar: nalar.
Penutup
Pertarungan antara ijtihad dan algoritma bukan sekadar perdebatan teknologi, melainkan perjuangan mempertahankan ruh kemanusiaan dalam beragama. Bahwa berpikir adalah ibadah, dan nalar adalah bagian dari iman.
Di masa depan, mungkin akan lahir ribuan aplikasi fatwa, tetapi hanya sedikit manusia yang masih berani berpikir perlahan dengan hati yang berdoa.
Dan mungkin, justru di sanalah letak kemuliaan sejati ijtihad: menjaga nyala akal di tengah dinginnya logika mesin.
| Paradigma Baru Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/20251112-Pemerhati-hukum-Lutfie-Natsir-SH-MH-CLa.jpg)
|
|---|
| Bagaimana Komunikasi Jadi Senjata |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/TRIBUN-OPINI-Egi-Arfandi-Mahasiswa-Sastra-Indonesia-UNM.jpg)
|
|---|
| Kampus Unggulan Terpusat di Jawa, tapi SDM di Daerah Kaya Nikel dan Gas Tertinggal |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/Prof-Dr-Zakir-Sabara-H-Wata-ST-MT-IPM-ASEAN-Eng-1-2862022.jpg)
|
|---|
| Ketika Negara Memberi Trauma |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/TRIBUN-OPINI-drRatih-Paradini-Dokter-Penulis.jpg)
|
|---|
| Siapa Penemu Benua Australia? James Cook atau Pelaut Makassar? |
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/TRIBUN-OPINI-Saparuddin-Santa-Peneliti-dan-Penulis.jpg)
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/2025-11-13-Prof-Hannani-Yunus.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/OPINI-Hafiz-Elfiansya-Parawu.jpg)



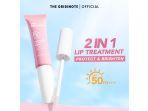




![[FULL] Belum Ada Bukti Ijazah Jokowi Asli Celah Roy Cs Lolos Pidana? Pakar: Bisa Digugurkan Hakim](https://img.youtube.com/vi/t9Sf51X9J4g/mqdefault.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/TRIBUN-OPINI-Egi-Arfandi-Mahasiswa-Sastra-Indonesia-UNM.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/Prof-Dr-Zakir-Sabara-H-Wata-ST-MT-IPM-ASEAN-Eng-1-2862022.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/TRIBUN-OPINI-drRatih-Paradini-Dokter-Penulis.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/TRIBUN-OPINI-Saparuddin-Santa-Peneliti-dan-Penulis.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/M-Yunasri-Ridhoh-Dosen-Pendidikan-Pancasila-UNM-p.jpg)

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.