Opini
Pemilu Bermartabat, Mungkinkah?
Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan harus menjadi tauladan, terutama dalam bingkai netralitas.
Pemilu Bermartabat Mungkinkah
Oleh: Aswar Hasan
Dosen Fisip Unhas
TRIBUN-TIMUR.COM - PEMILU adalah ajang kontestasi untuk memimpin suatu bangsa. Ia merupakan proses politik dalam bernegara guna melahirkan sosok negarawan.
Melalui pemilu, para pasangan calon berkompetisi saling menguji dan memberikan kesempatan bagi calon-calon yang memiliki visi, integritas, dan komitmen dalam mempersembahkan yang terbaik bagi negara dan bangsanya.
Perilaku berkeadaban dan berkecerdasan serta komitmen bagi setiap pasangan calon presiden, menjadi hal yang wajib untuk diuji secara berkeadilan, oleh semua pihak, terutama oleh penyelenggara negara, khususnya penyelenggara pemilu itu sendiri.
Tetapi tak kalah lebih penting dari itu semua, adalah sejauh mana kepala negara atau Presiden bisa memfasilitasi, membingkai dan mengarahkan agar penyelenggara bisa menunaikan tugas penyelenggaraanya secara independen dan profesional yang dinafasi norma kenegaraan secara subtansial yang berlangsung sesuai mekanisme prosedural legalistik yang objektif dan menjunjung tinggi etika bernegara.
Karenanya Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan harus menjadi tauladan, terutama dalam bingkai netralitas.
Pakar politik konstitusi, Profesor Larry Diamond dalam: “The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies Throughout the World”, 2008 telah mewanti-wanti tentang pentingnya Netralitas seorang Presiden dalam mengawal proses Pemilu dalam bernegara. Betapa tidak, karena netralitas seorang Presiden dalam penyelenggaraan pemilu menjadi hal yang sakral karena akan menjadi cermin perilaku bagi segenap aparatur kenegaraan dari level teratas, hingga ke level yang paling terbawah.
Karena itu, prinsip berkeadilan dan kebenaran yang harus tercermin dalam bentuk netralitas, menjadi kewajiban utama dan pertama yang harus dikedepankan bagi segenap penyelenggara negara, terutama kepala negara dan kepala pemerintahan (Presiden) tanpa di mulai dan dicontohkan oleh Presiden, maka Pemilu akan rentan dicederai melalui kuasa demi kekuasaan itu sendiri.
Itulah sebabnya para penguasa itu harus berbingkai aturan yang dijiwai etika guna memagari diri dalam merawat keadaban dalam bernegara.
Dalam pada itu, maka pemilu sebagai instrumen pokok dalam berdemokrasi harus berlangsung secara berkeadaban.
Tanpa itu, maka martabat suatu bangsa yang berkeadaban akan terhempas dicampakkan oleh pihak pemburu kekuasaan yang tak dinafasi oleh jiwa kenegaraan.
Alexis Dek Tocqueville (Democracy in Amerika, 1840) menyatakan pentingnya Pemilu yang fairness dalam melahirkan kepemimpinan yang responsif terhadap kehendak masyarakat.
Pemilu adalah mekanisme bagaimana mewujudkan kehendak masyarakat dalam pengelolaan negara melalui suatu pemerintahan bukan kehendak para politisi semata, apalagi dari sekumpulan pemburu kekuasaan demi pengabadian dan pemuncakan syahwat politik kekuasaan mereka, melalui pemilu.
Karenanya, pemilu harus dibingkai oleh aturan yang adil dan dinafasi oleh etika dalam bernegara.
Tanpa itu, pemilu hanya merupakan rangkaian prosedure kegiatan kenegaraan yang takkan mungkin bisa melahirkan negarawan yang menjadi penyangga utama kita kelak dalam bernegara.
Etika Bernegara
Bernegara tanpa dinafasi etika yang berbasis pada aturan perundang-undangan hanyalah sebuah fatamorgana yang menyesatkan dalam merengkuh cita- cita berbangsa.
Negara tanpa etika berbasis perundang-undangan cenderung disebut sebagai negara yang tidak beradab atau tidak berkeadilan.
Etika dan perundang-undangan memainkan peran penting dalam membentuk tatanan sosial dan hukum suatu negara, terutama dalam proses politik pemilu di suatu negara.
Para ahli Politik dan hukum, seperti Barry R. Weingast, Bruce Ackerman, hingga Francis Fukuyama, telah mengingatkan tentang pentingnya rule of law berbingkai demokrasi, dan perlunya dasar etika dalam berkonstitusi untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan menjadi otoritarian yang legalistik melalui proses politik.
Betapa tidak, implementasi sistem konstitusi yang kuat sekali pun, tanpa dasar komitmen etika yang kuat, bisa membuka dan menawarkan celah bagi praktik otoritarian yang mendapatkan legitimasi melalui proses politik.
Olehnya itu, implementasi pemilu yang bermartabat berdasarkan konstitusi dengan memperhatikan nilai-nilai etika dan prinsip demokratis menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan perlindungan hak-hak masyarakat.
Dengan demikian, praktik pemilu bermartabat menjadi urgen saat ini.
Dalam pada itulah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan agar seluruh kontestan Pemilu 2024 untuk tidak mengedepankan pragmatisme politik dan hanya mementingkan kemenangan.
Proses pemilu yang serba pragmatis dan oportunistis bisa mengakibatkan pendangkalan politik.
Seluruh pemangku kepentingan pemilu diharapkan menciptakan pemilu yang bermartabat sehingga bisa melahirkan sosok negarawan.
”Kami tidak ingin pendangkalan politik dan disorientasi kenegaraan terjadi karena proses pemilu yang serba pragmatis, yang serba oportunistis, yang hanya mementingkan kemenangan,” ujar Haedar saat diskusi ”Refleksi Akhir Tahun (Kompas,29/12/2023).
Persoalan yang demikian potensial membelenggu penyelenggaraan pemilu kali ini adalah netralitas penyelenggara negara dan/atau aparatur negara, yang dicurigai oleh segenap komponen masyarakat kritis, mulai dari tingkat pusat, hingga pemerintahan di daerah.
Kondisi tersebut, sebegitu menyulitkan penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), di semua level dalam menegakkan aturan pemilu.
NETRALITAS PRESIDEN
Jamuan makan Presiden kepada calon presiden Prabowo Subianto telah memicu interpretasi akan keberpihakan Presiden.
Oleh karenanya, hal itu kiranya tidak diinterpretasi sebagai sinyal dari presiden akan perlunya aparatur negara untuk memberikan dukungan serta. Meskipun, motifnya bisa saja bermaksud demikian.
Betapa tidak, karena jamuan makan yang disertai dialog pace to Pace itu, sarat nuansa antar persona yang bermuatan politik dalam konteks pemilu.
Akan berbeda halnya jika jamuan makan itu dilakukan kepada ketiga kontestan calon presiden, kesannya akan lebih bernuansa jamuan antara bapak bangsa kepada ketiga anak bangsa terbaik, dimana salah satunya kelak yang akan meneruskan kepemimpinannya di masa depan, sebagaimana dilakukan Presiden Jokowi sebelumnya.
Membandingkan kedua jamuan makan itu, publik pun menginterpretasikan bahwa jamuan makan pertama adalah sekadar pencitraan ke publik bahwa Presiden Jokowi akan netral.
Namun, jamuan makan yang terakhir, sudah mengesankan suatu keberpihakan.
Berbagai masalah yang membelenggu dan menyandera penyelenggaraan Pemilu 2024 itu tak lepas dari keinginan tokoh atau kelompok dalam masyarakat untuk hanya memenangi pemilu.
Prinsip dan tekad yang berorientasi pokoknya harus, bahkan, terasa tak peduli dengan kondisi bangsa, terutama terkait persatuan Indonesia dan pendewasaan rakyat dalam berdemokrasi (Tajuk Kompas, 30/12/2023).
Egoisme politik secara prakmatisme tersebut, potensial memicu kerusuhan politik yang akhirnya mengancam stabilitas nasional yang selama ini sedemikian kuat telah diupayakan untuk dirawat
. Kerentanan destabilitas politik akibat praktik pemilu yang tidak bermartabat, tidak boleh dipandang sebelah mata karena bisa serta memicu destabilitas di sektor lainnya.
Tentu, kepedulian seperti itu, hanya terjadi pada komponen anak bangsa yang terpanggil dan peduli akan kemaslahatan negaranya, karena prihatin pada situasi tersebut. Wallahu a’ lam Bishawwabe.(*)

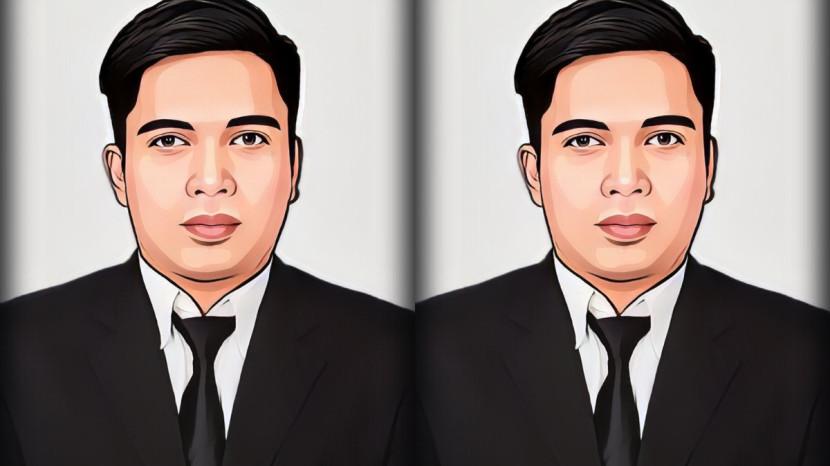



















Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.