Opini
Kuota 30 Persen Perempuan Hanya Manis di Regulasi
Kuota 30 persen perempuan dalam politik Indonesia belum menjamin ruang bicara yang setara. Kehadiran mereka kerap hanya jadi angka.
Kuota 30 Persen Perempuan Hanya Manis di Regulasi
Oleh: Endang Sari
Dosen Ilmu Politik FISIP Unhas
TRIBUN-TIMUR.COM - Saya terpikir pada pertanyaan mendasar yang pernah diajukan Gayatri Chakravorty Spivak, seorang filsuf sekaligus pemikir feminis asal India yang lahir pada tahun 1942 di Calcutta, British India, dalam esainya yang terkenal, Can the Subaltern Speak? “Bisakah yang tertindas berbicara?”.
Dalam tulisan itu, Spivak mempertanyakan apakah kelompok tertindas benar-benar bisa menyuarakan dirinya sendiri dalam sistem yang dibentuk oleh kekuasaan kolonial dan patriarki.
Spivak berargumen bahwa bahkan ketika subaltern berbicara, suara mereka sering disaring, diinterpretasikan, atau bahkan diabaikan oleh struktur dominan.
Pertanyaan ini bukan sekadar retoris, melainkan gugatan terhadap struktur kekuasaan yang membungkam suara-suara dari pinggiran.
Dalam konteks politik Indonesia, sayangnya, perempuan juga masih menjadi “subaltern” itu: hadir dalam angka, namun tidak dalam makna.
Legal Candidate Quotas pada pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, memng telah mengatur bahwa salah satu syarat untuk menjadi peserta pemilu adalah dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan di daftar bakal calon legislatif, begitu pula di pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik diatur bahwa dalam kepengurusan Partai Politik di tingkat pusat, harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.
Artinya, partai politik diwajibkan untuk menyertakan minimal 30 persen perempuan dalam struktur kepengurusan di tingkat pusat.
Ketentuan ini merupakan bagian dari upaya afirmatif untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik, tidak hanya sebagai calon legislatif tetapi juga dalam pengambilan keputusan internal partai.
Namun, kenyataan di lapangan jauh dari ideal.
Banyak partai yang hanya menjadikan perempuan sebagai pelengkap syarat administratif.
Mereka dicantumkan dalam daftar caleg, namun ditempatkan di nomor urut terakhir, tanpa dukungan logistik, tanpa pelatihan, dan tanpa peluang nyata untuk terpilih.
Bahkan, tak jarang perempuan hanya menjadi “caleg pelengkap” dipasang untuk memenuhi kuota, lalu ditarik mundur atau digantikan setelah pemilu usai.
Sistem pemilu kita, yang menganut proporsional terbuka, justru memperparah keadaan.
Dalam sistem ini, suara terbanyaklah yang menentukan siapa yang duduk di kursi legislatif.
Maka, caleg perempuan yang minim sumber daya dan jaringan politik akan sulit bersaing dengan caleg laki-laki yang telah lama eksis dalam struktur partai.
Di sinilah letak ironi itu: regulasi yang dimaksudkan untuk membuka ruang justru terjerat dalam sistem yang menutupnya kembali.
Keterpilihan perempuan di DPR dari pemilu ke pemilu pun tidak pernah mencapai 30 persen.
Jumlah perempuan terpilih di DPR untuk periode 2009-2014 hanya 17,86 persen, periode 2014-2019 hanya berjumlah 97 orang atau persen 17,32 persen dari jumlah kursi DPR.
Di 2019-2024 hanya 120 orang atau 20,87 persen, dan di tahun 2024-2029 hanya 127 orang atau 21,90 persen.
Spivak menyebut bahwa subaltern tidak bisa berbicara bukan karena mereka tidak memiliki suara, tetapi karena struktur kekuasaan tidak menyediakan ruang untuk suara itu didengar.
Dalam konteks politik kita, perempuan bukan tidak berbicara, perempuan telah bersuara, mencalonkan diri, berkampanye, bahkan menang.
Namun, suara perempuan sering kali dikooptasi, disaring, atau bahkan dibungkam oleh sistem yang masih sangat maskulin dan patronistik.
Ketika perempuan berhasil masuk ke parlemen, mereka kerap dihadapkan pada dilema representasi: apakah mereka benar-benar mewakili kepentingan perempuan, atau sekadar menjadi perpanjangan tangan elit partai?
Saya pernah berbincang dengan seorang teman caleg perempuan dari salah satu partai politik.
Ia bercerita bagaimana dirinya diminta maju oleh partai hanya tiga bulan sebelum masa kampanye dimulai. Tanpa dana, tanpa tim, dan tanpa pelatihan, ia merasa seperti dilempar ke medan perang tanpa senjata. “Saya tahu saya tidak akan menang,” katanya sambil tersenyum getir.
“Tapi saya diminta maju, katanya untuk memenuhi kuota.” Ia tertawa getir. “Saya ini cuma angka.” Angka. Itulah kata kuncinya. Perempuan dalam politik Indonesia kerap direduksi menjadi angka.
Tiga puluh persen. Sebuah angka yang tampak progresif.
Angka 30 persen dianggap sebagai angka minimal bagi perempuan untuk dapat memberi peran penting dan ikut serta dalam perumusan kebijakan.
Namun rasanya kosong makna jika tidak dibarengi dengan perubahan struktural. Kita sering lupa bahwa representasi bukan hanya soal kehadiran fisik, tetapi juga soal kuasa untuk berbicara, memutuskan, dan mengubah.
Tanpa itu, kehadiran perempuan hanya menjadi kosmetik demokrasi. Spivak mengingatkan kita bahwa representasi memiliki dua makna: representation sebagai penggambaran (re-presentation), dan representation sebagai perwakilan politik.
Dalam konteks pemilu, perempuan sering kali hanya direpresentasikan sebagai simbol kesetaraan, bukan sebagai agen perubahan.
Perempuan menjadi wajah yang ditampilkan untuk menunjukkan bahwa demokrasi kita inklusif, padahal di balik layar, keputusan tetap didominasi oleh suara-suara maskulin yang telah lama mengakar.
Lalu, bagaimana agar perempuan benar-benar bisa berbicara? Jawabannya bukan sekadar menambah angka kuota, tetapi membongkar sistem yang meminggirkannya.
Kita perlu meninjau ulang sistem pemilu proporsional terbuka yang lebih menguntungkan mereka
yang punya modal besar, terkenal dan punya relasi dengan kekuasaan.
Kita perlu mendorong demokratrisasi di internal partai politik untuk tidak hanya mencalonkan perempuan, tetapi juga membina, mendukung, dan menempatkan mereka di posisi strategis.
Kita perlu membangun budaya politik yang tidak memandang perempuan sebagai pelengkap, tetapi sebagai pemimpin yang setara.
Namun, lebih dari itu, kita perlu mendengarkan.
Mendengarkan suara-suara perempuan dari berbagai latar belakang: buruh, petani, nelayan, guru, dosen, tenaga kesehatan, ibu rumah tangga, aktivis, penyintas kekerasan.
Mereka yang selama ini berada di pinggiran, yang suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk politik elit.
Karena hanya dengan mendengarkan, kita bisa menjawab pertanyaan Spivak dengan jujur: ya, subaltern bisa berbicara jika kita bersedia diam, memberi kesempatan, dan mendengarkan. (*)
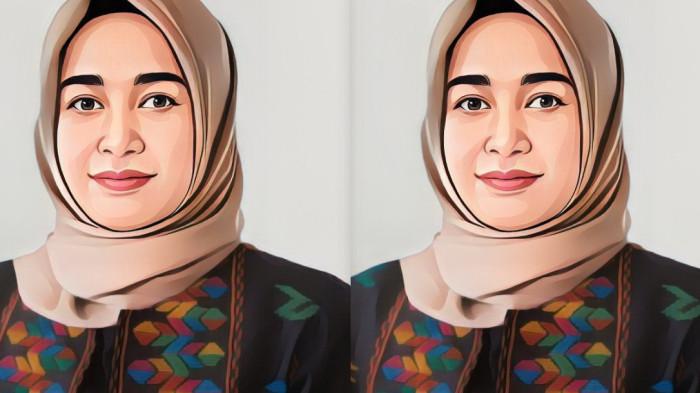



















Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.