Opini
Bulu Alauna Tempe dan Kitab Kuning: Orkestra Santri dari Danau Tempe untuk Dunia
Hari pembukaan Musabaqah Qiraatul Kutub Internasional di As’adiyah terasa seperti samudera kecil yang bernafas.
Nada-nadanya mengingatkan bahwa pemimpin harus tegak seperti gunung, mengayomi seperti pohon, dan tidak tenggelam oleh arus kekuasaan.
Lagu itu juga memperingatkan agar kekuasaan tidak memakan akar, karena benang kusut dan rakit yang tak seimbang bisa menenggelamkan siapa saja.
Dalam pembukaan MQK, lantunan lagu itu menjadi jembatan antara riak lokal dan gema internasional.
Dari situ kita paham: membaca kitab dan menyanyikan danau adalah dua ritual yang saling memperkaya.
Jika bait-bait Bulu Alauna Tempe diterjemahkan ke dalam bahasa hari ini, ia akan berbicara tentang limpahan rezeki yang tak pernah kering, tentang danau yang bukan hanya air tetapi rahim peradaban.
Inilah tafsir hidup masyarakat yang menggantungkan diri pada perahu, jala, dan ikan.
Dalam suara santri, makna itu seperti lahir kembali: bahwa kitab bisa dibaca dari lembaran kertas, tapi juga dari gelombang air dan riak-riak danau.
Kitab bisa dihafal lewat huruf Arab gundul, tapi juga lewat syair Bugis yang disulam dalam ingatan.
Danau Tempe sejak lama adalah nadi ekonomi Sulawesi Selatan. Nelayan menjaring ikan, pedagang perempuan menjual hasil tangkapan di pasar, dan rumah-rumah terapung menari di atas air.
Para peneliti dunia menegaskan hal itu.
Misalnya, Christian Pelras (1996, The Bugis) menulis bahwa Danau Tempe adalah contoh adaptasi ekologis luar biasa masyarakat Bugis: rumah berpindah mengikuti arus, ekonomi berdenyut dari ikan, dan budaya lahir dari air.
Begitu pula catatan VOC abad ke-17 lewat laporan Cornelis Speelman, yang menyebut kawasan rawa luas tempat rakyat hidup dari perairan, meski nama “Danau Tempe” belum dipakai.
Semua ini menunjukkan bahwa danau itu bukan sekadar bentangan air, melainkan teks besar yang selalu bisa dibaca ulang. Kerajaan-kerajaan di sekitar danau juga lahir dari denyut air ini.
Ajattapareng—aliansi kerajaan Sidrap, Suppa, Rappang, Sawitto—berdiri tak jauh darinya. Soppeng dan Bone menjalin persekutuan sekaligus persaingan.
Wajo, yang bernaung di tepi Danau Tempe, tampil dengan identitas egaliter: rakyat punya suara, pemimpin hanyalah pelaksana, bukan penguasa mutlak. A.A. Cense (1931) dalam kajiannya tentang Lontara Wajo menegaskan bagaimana struktur sosial Wajo memberi ruang musyawarah yang lebih luas ketimbang kerajaan lain.


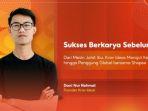

















Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.