Opini
Ditjen Pesantren: Antara Rekognisi dan Risiko Birokratisasi
Selama puluhan tahun, posisi pesantren dalam sistem hukum nasional seperti “anak tiri”.
Ringkasan Berita:
- Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren bertujuan memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi terhadap pesantren.
- Kehadiran Ditjen Pesantren membawa potensi masalah, seperti terseret dalam logika administratif, perubahan relasi menjadi transaksional akibat penyaluran dana, dan tumpang tindih kebijakan lintas kementerian.
- Keberhasilan Ditjen Pesantren bergantung pada keterlibatan kiai, pengasuh, dan asosiasi pesantren dalam perencanaan hingga evaluasi kebijakan.
Oleh: Rusdianto Sudirman
Dosen Hukum Tata Negara IAIN Parepare
TRIBUN-TIMUR.COM - Di sebuah pesantren kecil di pinggiran Sulawesi Selatan, seorang kiai sepuh pernah berujar, “Pesantren itu tidak butuh diurus negara. Tapi negara perlu belajar dari pesantren.”
Kalimat sederhana itu kini terasa relevan di tengah kabar pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di bawah Kementerian Agama.
Langkah pemerintah ini, bagi sebagian kalangan, dianggap sebagai tonggak sejarah untuk pertama kalinya pesantren memiliki direktorat jenderal sendiri setara dengan madrasah, haji, dan pendidikan Islam lainnya.
Tapi di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa negara mulai menancapkan kuku birokrasi ke dalam ruang spiritual dan sosial yang selama ini tumbuh mandiri di luar kendali kekuasaan.
Pertanyaan yang mengemuka, apakah Ditjen Pesantren ini benar-benar bentuk pengakuan (rekognisi) terhadap kemandirian pesantren, atau justru pintu masuk bagi proses birokratisasi dan politisasi lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara ini?
Selama puluhan tahun, posisi pesantren dalam sistem hukum nasional seperti “anak tiri”.
Ia tidak sepenuhnya di bawah sistem pendidikan formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), tetapi juga tak diakui secara otonom.
Banyak pesantren berjalan dengan dana mandiri, kurikulum sendiri, dan legitimasi sosial yang datang dari masyarakat, bukan dari negara.
Barulah pada Tahun 2019, lahirlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (UU Pesantren) sebuah tonggak penting dalam sejarah politik hukum pendidikan Islam di Indonesia.
UU ini menegaskan tiga fungsi utama pesantren yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
Ketiga fungsi itu menunjukkan bahwa pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat transformasi sosial dan ekonomi.
Namun, pengakuan hukum tidak otomatis mengubah kenyataan struktural. Banyak pesantren masih menghadapi ketimpangan akses terhadap sumber daya, pendanaan, dan kebijakan negara.
Karena itu, pembentukan Ditjen Pesantren dapat dibaca sebagai langkah lanjutan untuk menerjemahkan mandat UU tersebut dalam bentuk kelembagaan negara.
Dari perspektif hukum tata negara, kebijakan pembentukan Ditjen Pesantren seharusnya berangkat dari tiga pendekatan yaitu rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi.
Pertama, rekognisi berarti negara mengakui eksistensi pesantren apa adanya bukan menciptakannya. Negara datang untuk menghormati, bukan mengatur-atur.
Kedua, afirmasi berarti negara memberi perlakuan khusus untuk memperbaiki ketimpangan historis.
Pesantren selama ini hidup dari swadaya masyarakat kini saatnya negara memberi dukungan yang proporsional, misalnya dalam bentuk pendanaan, pelatihan tenaga pendidik, dan pemberdayaan ekonomi berbasis santri.
Ketiga, fasilitasi berarti negara membantu tanpa mengintervensi.
Pemerintah boleh mendorong penguatan kapasitas kelembagaan, tapi tidak boleh mengatur isi kurikulum, tradisi keilmuan, atau hubungan kiai-santri yang menjadi jantung pesantren.
Dalam semangat UU Pesantren, negara wajib menghormati kemandirian pesantren sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (2): “Pemerintah menghormati kekhasan dan kemandirian pesantren dalam penyelenggaraan pendidikan.”
Namun, optimisme itu tak boleh membuat kita buta terhadap potensi masalah.
Pertama, risiko birokratisasi. Dengan terbentuknya Ditjen, pesantren berisiko terseret dalam logika administratif seperti laporan, format, dan indikator.
Jika standar teknokratis terlalu dominan, ruh keikhlasan dan kemandirian dua nilai yang melekat pada tradisi pesantren bisa terkikis.
Kedua, potensi politisasi anggaran. Ketika Ditjen menjadi pintu resmi penyaluran dana, relasi pesantren dan kekuasaan bisa berubah menjadi transaksional.
Dalam situasi politik yang makin pragmatis, bantuan pemerintah bisa bertransformasi menjadi alat pembentuk loyalitas politik.
Ketiga, tumpang tindih kebijakan. Fungsi pesantren bersinggungan dengan banyak kementerian seperti Pendidikan, Ketenagakerjaan, hingga Desa. Tanpa koordinasi yang baik, kebijakan bisa saling bertabrakan.
Misalnya, lulusan pesantren yang punya kompetensi keagamaan atau kewirausahaan sering kali tidak diakui secara formal dalam sistem ketenagakerjaan nasional.
Agar Ditjen Pesantren tidak terjebak dalam jebakan birokrasi, pemerintah perlu membangun tata kelola partisipatif.
Artinya, kiai, pengasuh, dan asosiasi pesantren harus dilibatkan sejak tahap perencanaan kebijakan hingga evaluasi program.
Pesantren bukan sekadar objek kebijakan, tapi subjek yang ikut menentukan arah pembangunan pendidikan Islam.
Selain itu, kebijakan harus bersifat desentralistik dan kontekstual. Pesantren di Madura tak sama dengan pesantren modern di Bandung atau pesantren perempuan di Lombok.
Karakter dan kebutuhan mereka berbeda. Karena itu, kebijakan harus fleksibel, tidak seragam, dan mampu menghormati keragaman lokal.
Negara juga perlu mendorong penguatan tata kelola pesantren melalui pelatihan manajemen keuangan, pengelolaan wakaf produktif, serta digitalisasi administrasi. Dengan begitu, pesantren tetap otonom namun tetap akuntabel di hadapan publik.
Sejarah mencatat, pesantren adalah salah satu lembaga tertua yang membentuk wajah Islam Indonesia yang inklusif, toleran, dan berakar kuat pada budaya lokal.
Dari rahim pesantren lahir para ulama, pejuang kemerdekaan, hingga pemimpin moral bangsa.
Karena itu, kehadiran Ditjen Pesantren semestinya menjadi momentum rekognisi, bukan alat kontrol baru.
Negara boleh hadir, tetapi tidak mendominasi. Negara boleh membantu, tetapi tidak mengekang.
Jika Ditjen Pesantren mampu menjadi jembatan antara nilai-nilai tradisi dan kebutuhan modernitas tanpa menghilangkan roh kemandirian, maka ini bisa menjadi tonggak baru sejarah pendidikan Islam di Indonesia.
Tapi jika ia berubah menjadi sekadar “Direktorat urusan administrasi pesantren,” maka langkah ini hanya akan menambah panjang daftar reorganisasi birokrasi tanpa makna substantif.
Pesantren telah berabad-abad hidup tanpa “payung birokrasi,” dan justru karena itu ia bertahan.
Negara kini datang bukan untuk mengatur, melainkan mengakui. Tantangannya adalah menjaga agar rekognisi itu tidak berubah menjadi domestikasi.
Dalam konteks itu, pembentukan Ditjen Pesantren hanyalah awal. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa negara belajar menghormati ruang spiritual yang lahir dari masyarakat, bukan menundukkannya dalam sistem administratif.
Sebab, seperti kata kiai sepuh tadi, “Pesantren itu tidak butuh diurus negara. Tapi negara yang butuh belajar dari pesantren.”






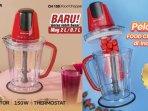





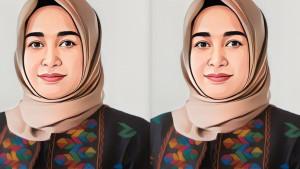

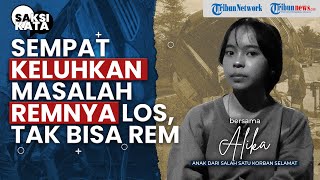





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.