Opini
Anggaran Daerah, oleh Siapa untuk Siapa?
Kebutuhan seperti apa? Tentu saja paling mendasar dalam kehidupan sosial: kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan.
Oleh: Andi Faisal
Dosen Universitas Negeri Makassar
TRIBUN-TIMUR.COM - PADA dasarnya, proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus melibatkan masyarakat, baik sebagai objek maupun subjek dari kebijakan anggaran itu sendiri.
Sebab, anggaran sejatinya bukan sekadar dokumen keuangan pemerintah, melainkan instrumen utama untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
Kebutuhan seperti apa? Tentu saja paling mendasar dalam kehidupan sosial: kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan.
Ketiga kebutuhan dasar ini harus dipenuhi melalui alokasi anggaran yang tepat, baik untuk pembangunan suprastruktur (kebijakan, program) maupun infrastruktur (fisik dan layanan dasar).
Dalam konteks itu, masyarakat seharusnya tidak hanya menjadi penerima manfaat anggaran, tapi juga dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunannya.
Gagasan partisipasi ini sebenarnya telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan secara teknis dijabarkan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017.
Namun sayangnya, filosofi dasar dari regulasi tersebut jarang tersampaikan secara utuh ke tingkat pemerintah daerah.
Yang banyak dipahami justru sebatas kulit luarnya saja—yaitu petunjuk teknis pelaksanaan.
Akibatnya, pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran, seperti melalui forum Musrenbang, kerap menjadi sekadar seremonial tahunan dan formalitas administratif.
Dalam kacamata teori Tangga Partisipasi Arnstein, realitas partisipasi masyarakat di Indonesia masih berada pada tingkat tokenisme—yakni bentuk partisipasi simbolik yang memberi ruang bicara tanpa kekuatan untuk memengaruhi keputusan.
Sementara itu, jika ditinjau dari teori Agency, posisi eksekutif sebagai agen memiliki dominasi penuh terhadap informasi, otoritas, dan teknokrasi dalam penyusunan anggaran.
Ketimpangan ini memudahkan praktik partisipasi semu, di mana masyarakat dilibatkan hanya sebatas prosedur, bukan pengambil keputusan sejati.
Minimnya partisipasi yang substantif dalam proses penyusunan anggaran daerah berdampak langsung pada kualitas kebijakan yang dihasilkan.
Program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD kerap tidak mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
Aspirasi warga hanya hadir dalam bentuk “catatan,” bukan dalam wujud anggaran dialokasikan.
Akibatnya, banyak program bersifat top-down—disusun secara teknokratis pemerintah tanpa dialog berarti dengan warga—sehingga tidak jarang terjadi ketidaksesuaian belanja dan kebutuhan lokal.
Sementara itu, masyarakat di perdesaan masih kekurangan akses air bersih, jalan lingkungan yang layak, dan tenaga pengajar di sekolah dasar.
Ironisnya, dari sisi kebijakan fiskal, struktur APBDpun mencerminkan kecenderungan serupa.
Pada APBD 2024, Pemprov Sulawesi Selatan mengalokasikan lebih dari Rp5,8 triliun untuk belanja tidak langsung—mencakup belanja pegawai dan barang birokrasi—atau lebih dari separuh total belanja daerah.
Ini menyisakan ruang yang sempit untuk belanja produktif yang langsung menyentuh rakyat.
Namun demikian, tidak semua kepala daerah mengikuti arus yang sama.
Beberapa pimpinan daerah di Sulsel secara tegas menolak pengadaan kendaraan dinas baru dan justru mengalihkan anggaran tersebut untuk perbaikan jalan dan pelayanan publik.
Saat ini, pemerintah daerah tengah memasuki proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
Harapannya, penyusunan anggaran tidak lagi bersifat teknokratis dan tertutup, tetapi benar-benar menyerap aspirasi publik melalui forum-forum partisipatif, seperti hasil reses DPRD, musrenbang, dan dialog warga.
Tanpa keterlibatan yang bermakna, anggaran hanya akan menjadi daftar belanja rutin—bukan alat transformasi dan keadilan sosial.(*)
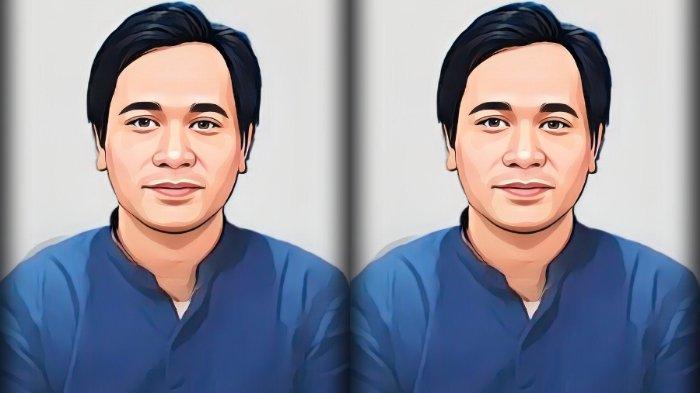
















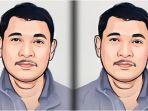



Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.