Opini
Merubah Sistem Menggerus Kebebasan
Pilkada (tepatnya pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota), kembali menarik untuk dibincangkan.
Oleh: Saiful Mujib (Anggota KPU Kabupaten Pangkep)
TRIBUN-TIMUR.COM- Akhir-akhir ini, wacana terkait Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada (tepatnya pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota), kembali menarik untuk dibincangkan.
Sejak disebut-sebut berbiaya mahal, khususnya oleh kosong satu di Republik ini, santer diwacanakan pemilihan kepala daerah akan dikembalikan dan dilakukan oleh DPRD.
Pertanyaannya, benarkah solusi dari "mahalnya" pilkada adalah mengembalikan pemilihan ke DPRD?
Sebelum menjawabnya, ada beberapa kajian yang menarik untuk diurai.
Pertama, pilkada yang sudah sekian tahun berlangsung dengan mengedepankan prinsip LUBER, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, memberikan ruang yang besar bagi setiap pemilih tanpa terkecuali untuk menentukan pilihannya.
Menentukan salah satu dari sekian calon yang maju menjadi kontestan, yang menurut pemilih terbaik dan akan dipilihnya di TPS.
Memilih calon dari sekian calon yang menurut pemilih terbaik, bagi penulis adalah sesuatu yang lebih mahal dari apapun, bahkan tidak dapat dinilai dengan uang atau emas sekalipun.
Setelah perjuangan menumbangkan otoritarian yang sudah berlangsung puluhan tahun sejak Indonesia merdeka.
Memilih langsung wakil rakyat atau pemimpin di suatu daerah menjadi uforia yang tak terbantahkan oleh banyak kalangan.
Hanya saja, efek dari pemilih memilih langsung wakil dan pemimpin tersebut, yang kemudian mendorong beberapa pihak untuk berkreasi mencari cara yang efektif untuk mendekati pemilih.
Kenapa harus pemilih, karena pemilih adalah setiap orang yang telah memenuhi syarat, yang kemudian didaftar oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, untuk kemudian ditetapkan secara berjenjang, dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat nasional.
Pemilih yang telah ditetapkan tersebut berhak untuk mendapatkan pelayanan di TPS atau tempat pemungutan suara.
Dalam konteks ini saja, kita sudah melihat efek positif dari ditetapkannya pemilih di hari pemungutan suara. Pemilih memiliki kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam pemilu maupun pemilihan.
Setiap pemilih memiliki hak yang sama dengan siapapun, tanpa ada sekat baik karena status sosial atau keyakinan.
Setiap orang yang masuk kategori pemilih memiliki kemerdekaan dan kemandirian untuk menentukan pilihannya.
Hal inilah yang kemudian mendorong kontestan dalam hal ini calon atau pasangan calon, untuk berkreasi menemukan cara yang tepat untuk mendekati pemilih.
Model pendekatannya pun berlangsung dengan sangat variatif.
Ada yang melakukannya dengan model penyadaran, mengajak pemilih peduli dengan pilkada, dengan terlebih dahulu meningkatkan kemauan dan kesadaran akan pentingnya pilkada dan pentingnya memilih pemimpin yang diharapkan.
Ada juga yang melakukan dengan pendekatan praktis, dengan waktu yang singkat, tanpa memperdulikan kesadaran pemilih.
Melakukan kegiatan yang sifatnya instan namun tujuannya sama, yaitu mengajak pemilih mendukung kontestan tertentu.
Dan tidak menutup kemungkinan ada kontestan yang menggabungkan kedua model tersebut.
Dalam perkembangannya, dari model pendekatan tersebut, sepertinya pendekatan praktis lebih dominan dan cenderung dilakukan oleh kontestan.
Mungkin karena memiliki modal materi yang cukup. Atau karena memiliki modal sosial yang besar, sehingga elektabilitas tinggi.
Atau karena pemahaman bahwa, untuk menyadarkan pemilih membutuhkan waktu yang tidak singkat.
Namun faktanya, tidak sedikit masyarakat dan pemilih yang terlanjur menyukai yang instan-instan. Bahkan biasanya tidak mempedulikan efeknya.
Selama dapat segera dinikmati maka akan diterima.
Penelitian dan survei KPU Provinsi Sulawesi Selatan di pilkada empat tahun silam, yaitu pilkada tahun 2020 dapat menjadi data pembanding.
Misalnya data untuk kabupaten Pangkep (Pangkajene dan Kepulauan) saja, ada lebih dari 29 persen warga pemilih yang setuju terhadap imbalan langsung dari kontestan.
Sementara di sisi lain, konsep dan cara pandang pemilih kian bertransformasi mengikuti perkembangan zaman.
Hampir setiap hari bahkan setiap menit kita mengkonsumsi informasi dari manapun dan siapapun. Sadar atau tidak kita mengenal dan mengadopsi budaya dan kebiasaan baru.
Dan harus diakui perkembangan informasi disatu sisi sangat besar pengaruhnya, bahkan dapat berimplikasi pada terkikisnya empati sosial.
Membuat sebagian dari kita cenderung abai terhadap norma dan kearifan lokal yang turun temurun dipraktekkan oleh leluhur kita.
Bisa jadi, inilah yang mendasari sebagian pemilih, sehingga tanpa berfikir panjang, mengambil imbalan yang diberikan kontestan.
Memanfaatkan cara yang singkat untuk mendapatkan keuntungan.
Sementara, ada sebagian pemilih "dipaksa" untuk menjadi ketergantungan dengan berbagai macam bantuan, yang sifatnya cuma-cuma.
Banyak program pemerintah yang bersifat langsung, berupa bantuan uang tunai atau barang kebutuhan sehari-hari, sehingga semakin melanggengkan situasi tersebut.
Akhirnya memberikan peluang bagi sebagian kontestan yang melihat perilaku ketergantungan tersebut sebagai pintu masuk.
Terjadinya praktek vote buying, jual beli suara, politik transaksional, money politik, intervensi dan tekanan, mungkin salah satunya karena efek dari sifat ketergantungan ini.
Perilaku yang timbul karena perspektif ini tentu saja sangat merugikan, terutama bagi kontestan yang harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk mempengaruhi pemilih. Bagaimana dengan kontestan yang memiliki modal pas-pasan, atau bahkan tidak memiliki modal?
Bisa jadi akan berfikir dua tiga kali untuk melanjutkan langkahnya. Atau tetap maju menjadi calon atau pasangan calon, namun dengan cara menggandeng pihak tertentu yang memiliki modal.
Pertanyaannya, tidak adakah kontestan yang menerapkan model pertama, bermodalkan kepercayaan publik, bermodalkan pengalaman, bermodalkan program kerja dan visi misi yang rasional sehingga mampu meyakinkan pemilih.
Atau melakukan gerakan penyadaran kepada pemilih, dan kemudian terpilih. Seratus persen, Saya meyakini ada. Di beberapa tempat walaupun skalanya berbeda dari pemilihan bupati atau wali kota dan bahkan gubernur, keterpilihan pemimpin justru karena harapan dan dorongan dari warga pemilih sendiri. Sehingga seorang calon maju dan kemudian terpilih.
Artinya, dari sekian persen pemilih yang masih ketergantungan terhadap imbalan atas jasanya menyalurkan hak pilihnya.
Angka pemilih dan masyarakat yang dengan kesadarannya datang ke TPS, menginginkan keterpilihan pemimpin yang di idam-idamkan tanpa memerlukan imbalan, jauh lebih besar.
Masih dari hasil survei yang sama yang saya kemukakan di atas. Ada lebih 49 persen pemilih yang benar-benar mengaku tidak membutuhkan imbalan atas suara yang disalurkannya di TPS.
Tesis lain adalah tidak akan ada transaksi jika tidak ada penjual dan pembeli. Penjual atau dalam konteks ini adalah pemilih, dan pembelinya adalah kontestan.
Problem pemilih bisa jadi karena faktor ketidak tahuan. Iming-iming akan imbalan bisa saja tidak akan menarik dan diterima, ketika dibarengi pemahaman terkait dengan efek negatif dari menerima imbalan yang diberikan oleh kontestan.
Atau bisa jadi pemilih mengetahui efeknya, namun karena "terpaksa", sehingga pemilih cenderung menafikkan dampak yang belum tentu akan dihadapinya. Sementera problem kontestan tentu saja terkait dengan komitmen menjalankan aturan.
Wacana terkait mahalnya kendaraan politik juga perlu diperhatikan. Bahkan, seorang calon atau pasangan calon yang akan maju menjadi kontestan harus mengeluarkan biaya lebih mahal, jika dirinya bukan merupakan kader partai politik.
Setidaknya itu yang menyeruak ke permukaan dan menjadi pembicaraan banyak orang. Jika tesis ini benar adanya, bisa jadi inilah salah satu penyebab sehingga statemen terkait mahalnya pilkada ini mengemuka. Lalu, apakah solusinya adalah mengembalikan pemilihan ke DPRD? Apakah kita tidak sedang memindahkan tempat "masalah", yang bisa saja praktek di atas bukan justru hilang, namun menjadi lebih terstruktur, rapi dan lebih besar. Namun yang pasti, jika ini benar (Gubernur, Bupati, Walikota di pilih DPRD), maka pemilih tidak lagi bebas dan merdeka dalam menentukan pilihannya.
Sebagai bagian dari sistem, penulis berharap upaya perbaikan dari situasi yang dianggap masalah hari ini adalah dengan memperketat pengawasan dan penegakan hukum.
Selanjutnya merajut aturan main yang benar-benar susai dan dibutuhkan.
Bukan kemudian menggerus kedaulatan rakyat yang sejak puluhan tahun terakhir, khususnya pasca reformasi, beruforia merayakan kebebasannya.(*)

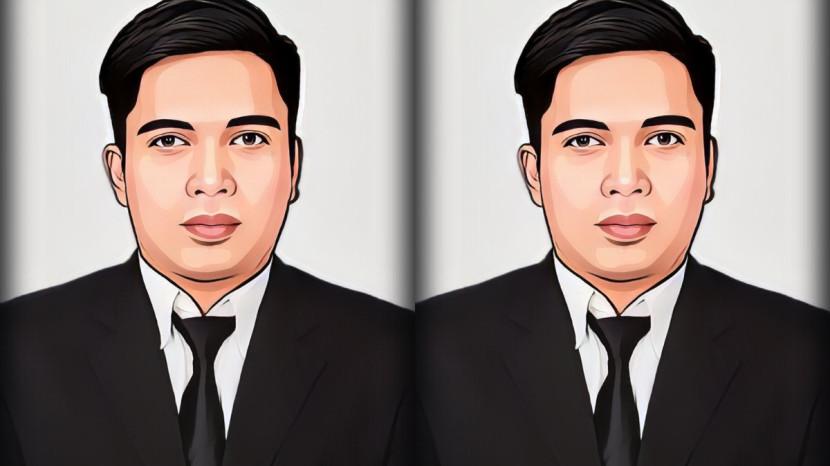



















Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.