Opini
Arus Balik Kebudayaan: Lokalitas dan Poskolonialitas
Aksesoris tradisional yang sangat lekat dengan pesta pernikahan orang-orang di Sulawesi Selatan dan Barat. Suku Bugis atau Makassar?
Oleh: M. Fadlan L Nasurung
Yayasan Nalarasa
TRIBUN-TIMUR.COM - Siapakah gerangan yang memiliki hak paten atas baju bodo, songkok recca dan sigerra?
Aksesoris tradisional yang sangat lekat dengan pesta pernikahan orang-orang di Sulawesi Selatan dan Barat. Suku Bugis atau Makassar?
Tulisan kali ini, salah satunya terinspirasi oleh perdebatan semisal di sejumlah grup sejarah dan budaya di laman facebook.
Perdebatan yang sebenarnya menggelitik tetapi sekaligus memiriskan hati.
Sebab, tidak jarang berujung saling klaim, saling tuding bahkan saling mencaci-maki dengan ego kesukuan yang kental.
Kenyataan tersebut adalah fragmen kecil dari fenomena gunung es krisis sejarah dan kebudayaan bangsa.
Sejarah Lokal
Penulis kerap membatin, ternyata warisan politik pecah belah kolonial begitu kuat mencengkram alam bawah sadar bangsa ini.
Salah satu yang menyebabkan Indonesia terus-menerus berada dalam bayang-bayang kolonialisme hingga kini, karena historiografinya yang sangat lemah dan memang tidak mendapatkan perhatian berarti dari para pemangku politik-pemerintahan.
Nasib sejarah lokal lebih memilukan lagi, minim atau bahkan tidak dilirik sama sekali.
Kita seringkali lebih disibukkan oleh perbincangan sejarah negeri di benua seberang, sehingga lupa menemukenali sejarah negeri dan kampung halaman sendiri.
Bahkan, orang-orang terpelajar lebih berbangga diri menjadikan para pemikir dari benua biru sebagai simbol kecemerlangan ilmu pengetahuan.
Tokoh-tokoh lokal dianggapnya hanya mewariskan mitos-mitos, itupun karena mitos sendiri telah disalahpahami dan dianggap sama dengan takhayyul dan khurafat.
Menyedihkannya, karena seringkali sejarah dan warisan kebudayaan lokal baru terasa begitu berharga jika dipresentasikan oleh orang-orang dari negeri seberang benua.
Apa yang patut dibanggakan dari sikap mengandalkan lisan/pikiran orang lain (outsider) untuk mendefinisikan kebudayaan negeri sendiri?
Kritik atas Sukuisme
Sejarah Nusantara yang berbasis kebudayaan dan ketatanegaraan, pasca kolonialisasi telah berubah menjadi sejarah suku-suku yang ahistoris.
Konstruksi kesukuan/etnisitas adalah bias orientalisme dalam membaca bangsa-bangsa timur.
Kesukuan/etnisitas adalah konstruk sosial masyarakat benua (kontinental) yang terkunci daratan (land locked). Karl Marx menyebutnya masyarakat komunal primitif.
Mereka membangun supremasi kelompok berbasis keluarga-keluarga kecil karena keterbatasan sumberdaya ekonomi.
Sehingga, sumberdaya ekonomi harus dikelola dan dipertahankan secara bersama-sama dengan sistem paternalistik.
Identitas kesukuan yang merupakan produk pemetaan sosial lewat antropologi-etnologi Eropa sentris abad 18-19, diaminkan tanpa kritik dan dengan bangga diwarisi hingga kini.
Pengelompokan masyarakat Nusantara dalam kategori etnik/suku mulai terjadi saat kolonialisasi.
Proyek raksasa pemetaan sosial yang dilakukan kolonial adalah agenda politik pengetahuan.
Belakangan kita mengenal politik identitas yang dahulu digunakan Belanda sebagai alat memecah belah (devide et impera).
Studi-studi bahasa dan budaya dilakukan secara masif saat era kolonial. Konstruk pengetahuan baru tentang identitas etnik berbasis bahasa dibentuk.
Dikotomi sosial secara perlahan terjadi. Orang-orang lalu merasa berbeda karena perbedaan bahasa, dan mengindentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok etnik tertentu.
Perasaan berbeda itulah yang secara berkelanjutan mengkristalisasi perbedaan identitas kesukuan.
Nicolaas Adriani dan Albertus Christiaan Kruyt adalah dua teolog dan etnolog Belanda yang berperan penting dalam pemetaan sosial masyarakat berdasarkan bahasa di Sulawesi.
Pendekatan etnologinya dalam pengelompokan bahasa-bahasa, banyak dijadikan rujukan sebagai dasar pembentukan kategori etnik/kesukuan, khususnya di Sulawesi Selatan dan Barat kini.
Jika kesukuan/etnisitas memang benar adanya, harus dicari terlebih dahulu siapa kepala/pemimpin suku Bugis, Makassar, Mandar, Toraja dan suku-suku lainnya?
Kalau tidak ditemukan, patutlah dipertanyakan, bagaimana mungkin sebuah struktur sosial tidak memiliki kepemimpinan?
Sejak kapan orang-orang di Nusantara dan Sulawesi khususnya mulai mengidentifikasi dirinya berdasarkan kesukuan/etnisitas itu?
Sebab, jangan sampai kita disibukkan oleh perdebatan tentang imajinasi sosial yang sebenarnya tidak memiliki akar dalam sejarah dan kebudayaan negeri ini.
Kesukuan diimajinasikan sebagai identitas bersifat kodrati (given), paten dan tetap (fixed).
Padahal identitas itu sendiri adalah sesuatu yang bersifat cair dan dinamis, mengikuti pola-pola perubahan dan perkembangan masyarakat dengan akar sejarah dan kebudayaan tertentu.
Identitas kesukuan itu bukanlah kodrat, tetapi konstruksi sosial yang dibangun lewat persepsi-imajinasi untuk membangun ikatan-ikatan mental-psikologis.
Itulah mengapa, identitas lebih dekat dengan emosi dari pada akal budi.
Ia dapat menjadi alat membangun imajinasi persatuan, sekaligus dapat digunakan sebagai alat melancarkan sentimen permusuhan dan perpecahan berbasis kelompok/golongan.
Poskolonialitas
Jika kita mengamini konsep sosial sukuisme dalam membaca Nusantara, berarti kita sekaligus mengatakan leluhur kita sebagai orang-orang primitif yang tak mengenal kebudayaan dan ketanegaraan.
Justru itulah justifikasi bangsa-bangsa Eropa melakukan kolonialisasi dalam rangka memperadabkan (civilize) bangsa-bangsa timur yang dianggapnya masih primitif.
Bisa jadi itu pula sebabnya, saat kita membicarakan perihal leluhur, memori yang mengendap di alam bawah sadar adalah mereka lekat dengan kehidupan primitif; kolot, jumud, terbelakang, penganut animisme-dinamisme dan label stigmatik lainnya.
Darimana bayang-bayang stereotip ini berasal? Tentu dari informasi kemana kiblat pengetahuan kita arahkan.
Mentalitas inlander; perasaan rendah diri yang akut di hadapan bangsa-bangsa lain (inferiority complex) akan dengan mudah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari.
Itulah mengapa, poskolonialitas menjadi jembatan penting menuju kemerdekaan yang telah dirintis oleh para pendiri republik ini.
Poskolonialitas mendesak untuk dilanjutkan sebagai agenda pembebasan dari kolonialisasi yang jejaknya masih nyata di berbagai lini.
Baik kolonialisasi yang berbaju ilmu-ilmu sosial positivistik, maupun yang berjubah teologi puritanistik.
Lalu, dapatkah lokalitas mendapatkan ruang untuk berbicara sebagai subjek untuk melakukan dekolonialisasi ilmu pengetahuan? Meminjam pemikir poskolonial Gayatri C. Spivak; Can Subaltern Speak?
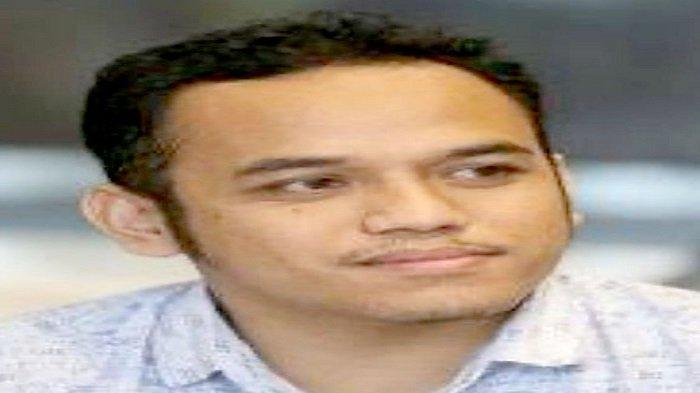


















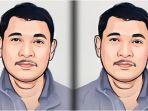


Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.