Restorasi Lahan, Penggurunan dan Ketahanan terhadap Kekeringan
Penetapan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kesadaran tentang lingkungan dan mendorong perhatian
Oleh: Muhammad Arsyad
Guru Besar Fisika Ekosistem Karst di Jurusan Fisika FMIPA UNM Makassar
SEJATINYA hari ini 5 Juni 2024 merupakan Hari Lingkungan Hidup se Dunia yang awalnya ditetapkan dalam Sidang Umum PBB tahun 1972 untuk menandai pembukaan Konferensi Lingkungan Hidup di Stockholm membutuhkan lebih banyak orang untuk memberikan atensi terhadap lingkungan.
Penetapan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kesadaran tentang lingkungan dan mendorong perhatian dan tindakan politik di tingkat dunia. Sehingga setiap tahun diangkat tema berbeda yang bertujuan menggugah kesadaran umat manusia untuk selalu menjaga ekosistem bumi demi kelangsungan hidup manusia.
Tahun 2024 ini, mengusung tema “Land restoration, desertification and drought resilience” yang penulis menerjemahkan bebas seperti judul tulisan ini.
Kerajaan Arab Saudi menjadi tuan rumah Hari Lingkungan Hidup se Dunia tahun ini dengan fokus pada restorasi lahan, penggurunan, dan ketahanan terhadap kekeringan. Artinya, tema tahun 2024 ini diarahkan untuk mewujudkan bagaimana lahan (hutan, permukiman, pantai, pesisir, mangrove, dan lainnya) untuk dilakukan restorasi, dan pencegahan terjadinya penggurunan, dan ketahanan penduduk bumi terhadap kekeringan. Tiga kata kunci ini menjadi tantangan utama bagi pemangku kepentingan untuk terus berbuat nyata demi terwujudnya ekosistem yang lebih baik. Restorasi lahan adalah pilar utama dekade restorasi ekosistem PBB (2021-2030), sebuah seruan untuk perlindungan dan kebangkitan ekosistem di seluruh dunia, yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Restorasi merupakaan suatu proses untuk membantu memulihkan suatu ekosistem yang telah terdegradasi, telah mengalami kerusakan atau mengalami kehancuran. Hal ini merupakan suatu kegiatan yang disengaja dilakukan untuk menginisiasi atau mempercepat proses ekologi. Restorasi merupakan suatu upaya untuk mengembalikan unsur biotik baik flora maupun fauna serta unsur abiotik (tanah, iklim, topografi dan lainnya) pada kawasan tertentu, sehingga tercapai keseimbangan hayati. Restorasi ekologi (ekosistem) ini dapat dilakukan melalui penanaman, pengayaan, permudaan alam dan atau pengamanan ekosistem. Artinya terdapat beberapa alasan, mengapa restorasi harus dilakukan, yakni: (1) lahan yang sehat mendukung eksosistem yang sehat, (2) degradasi lahan merupakan tantangan besar di seluruh dunia, (3) memulihkan lahan memerlukan pendekatan yang berbeda-beda, (4) restorasi lahan memegang peranan penting dalam pencegahan perubahan iklim, dan (5) pemangku kepentingan lokal adalah aktor utama keberhasilan restorasi lahan. Kelima alasan ini menjadi penting, karena ekosistem yang tidak sehat menyebabkan berbagai penyakit yang terus berkembangbiak dan menimbulkan kerugian harta bahkan nyawa. Covid-19 sebagai contoh tahun 2020 masih menghantui penduduk bumi sampai saat ini. Kesetimbangan ekosistem yang terus terjaga adalah salah satu faktor pendukung untuk menjaga kelestarian kehidupan di bumi, termasuk kehidupan manusia. Degradasi lingkungan tidak hanya “menghantui” negara berkembang, namun seluruh dunia. Lingkungan yang terus mengalami tekanan, lambat laun akan memberikan reaksi di luar pemikiran manusia. Banjir di Kabupaten Luwu, sekitar bulan lalu adalah bukti nyata, bagaimana lahan hutan telah bermetamorfosis yang sejatinya sebagai penadah hujan berubah menjadi awal mula bencana yang dampaknya masih terasa sampai saat ini. Masih banyak contoh lain dan akan terus terjadi bencana lingkungan yang lebih besar, jika ekosistem hutan hanya dipandang sebagai sumber ekonomi. Bahan tambang yang dimilikinya memang menjadi “gadis cantik” yang terus dilirik oleh investor. Namun lirikan ini tidak membuat pengambil kebijakan untuk meraup pundi-pundi ekonomi dan kepentingan sesaat untuk tergoda. Alasan untuk meningkatkan kesejahteraan warga menjadi bumerang sebagai penghancur masa depan warga yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.
Pemulihan lahan membutuhkan waktu panjang dan tidak mudah. Boleh jadi biaya yang diperlukan jauh lebih besar dari pada manfaat awal yang diperoleh. Penulis berharap agar pengambil keputusan benar-benar melakukan kajian mendalam terhadap permintaan investor untuk melakukan penambangan, misalnya. Artinya, pengambil kebijakan harus memerhatikan kepentingan yang lebih luas dan memberikan perhatian lebih dalam pada saat melakukan pendekatan. Pendekatan yang dilakukan tidak harus sama pada setiap kejadian. Masyarakat adat misalnya adalah komunitas yang harus dilibatkan dan didengar “suaranya” pada setiap pengambilan keputusan.
Sejatinya, isu lingkungan adalah isu krusial dalam pencegahan perubahan iklim. Sadar atau tidak, saat ini terjadi, lingkungan tidak baik-baik saja, Sampai awal Juni ini, masih terjadi hujan yang sifatnya frontal. Musim hujan sulit diprediksi kapan berakhir, begitu juga musim kemarau. Warga masyarakat harus terus diberikan edukasi untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan perilaku cuaca dan lainnya, Adaptasi bukan hanya pada prilaku, tetapi juga pada perubahan pola pikir untuk mencermati keadaan lingkungan. Prilaku warga yang masih mengabaikan isu lingkungan membuat kurangnya kesadaran terhadap kemampuan lingkungan untuk memberikan perlindungan, Sebatang pohon misalnya, menghasilkan oksigen untuk proses transpirasi manusia. Begitu juga sebaliknya, manusia membuang karbondioksida untuk tumbuh-tumbuhan. Jadi terdapat simbiosis mutualisme, dan saling terjadi ketergantungan. Selama terjadi proses ketergantungan dan terpenuhinya kebutuhan antar makhluk hidup, ketergantungan makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya, dan kesetimbangan lainnya dalam eksosistem, maka kerusakan lingkungan dapat teratasi. Kerusakan yang terjadi bisa berupa penggurunan dan lainnya.
Pengguruan dapat dikatakan sebagai proses yang terjadi pada lahan yang awalnya berproduksi dengan baik, namun berubah menjadi gurun atau lahan yang bermasalah. Encyclopedia Britannica mendefinisikan desertification atau penggurunan sebagai proses dimana alam atau manusia menyebabkan terjadinya penyusutan produktivitas biologis dari lahan kering. Penyusutan produktivitas tersebut dapat saja disebabkan oleh aktivitas manusia. Aktivitas ini pada awalnya mempunyai tujuan yang baik, namun dalam proses selanjutnya mengabaikan fungsi lahan dan carring capasity lahan, seperti pemanfaatan rerumputan secara berlebih, pembuatan irigasi yang tidak mengindahkan prinsip keberlanjutan, kemiskinan, ketidakstabilan politik atau gabungan faktor penyebab tersebut. Akibat lainnya, yang juga merupakan aktivitas manusia seperti perubahan iklim dan penggundulan hutan (deforestasi). Praktik pertanian yang dilakukan juga memberikan sumbangan cukup berarti. Pembukaan lahan pertanian tanpa analisis lingkungan yang memadai menyebabkan erosi tanah di berbagai belahan dunia, 100 kali lebih cepat dibandingkan dengan apabila terjadi secara alami. Gurun berarti lahan luas yang berupa hamparan pasir sejauh mata memandang, tidak ada, atau amat sangat jarang, tumbuhan hijau dan hidupan liar serta hampir tidak ada hujan. Bayangan kita bisa terwujud seperti yang terjadi di kawasan karst Maros Pangkep jika dilihat dari udara, perubahan fungsi lahan sudah menjadi kejadian yang di”biasa”kan> Perubahan ini secara cepat akan berubah seperti hamparan gurun pasir di Nusa Tenggara atau bagi yang melaksanakan haji adalah hamparan pasir di Arab Saudi.
Kejadian penggurunan atau desertifikasi adalah masalah yang terus berkembang, dan banyak dialami oleh negara-negara yang memiliki wilayah kering atau semi-kering. Di wilayah tersebut, ekosistemnya sendiri sudah dalam kondisi rapuh akibat kurang dan tidak teraturnya curah hujan. Penggurunan, akan lebih memperburuk habitat dan ekosistem alami diantaranya dalam bentuk berkurangnya ketersediaan sumber daya air, mengakibatkan hambatan terhadap produktivitas pertanian, pada gilirannya akan menyebabkan terganggunya ketahanan pangan dan meningkatkan taraf kemiskinan. Bagi masyarakat yang mengandalkan penghidupannya kepada ketersediaan sumber daya alam, tentu kondisi tersebut memberikan tekanan hidup yang lebih berat dan meningkatkan kerentanan serta menurunkan taraf ketangguhannya. Dampak degradasi lahan kemudian dirasakan oleh sebagian besar populasi dunia, diantaranya berupa perubahan dan gangguan pola curah hujan, memicu cuaca ekstrim, seperti banjir atau kekeringan, serta kejadian terkait perubahan iklim lainnya. Pada akhirnya, dalam kehidupan sehari-hari hal tersebut akan menciptakan ketidakstabilan sosial dan politik yang memicu peningkatan konflik, kemiskinan dan migrasi masyarakat dalam mencari tempat yang lebih mendukung kehidupan.
Perubahan lahan telah terjadi di 70 persen wilayah yang tidak tertutupi es, dan memengaruhi setidaknya 3,2 milyar populasi. Jika ini dibiarkan, bukan tidak mungkin perubahan akan mencakup 90 % wilayah pada tahun 2050. Badan PBB yang mengurusi program lingkungan (UNEP - United Nation Environment Programme) menunjukkan bahwa desertifikasi telah mempengaruhi 36 juta km2, berpengaruh terhadap setidaknya 250 juta orang serta diperkirakan 135 juta orang dipaksa untuk pindah dari tempat mereka tinggal pada tahun 2045 nanti. Ini adalah krisis kemanusiaan yang sangat perlu mendapatkan perhatian. Afrika tercatat sebagai benua yang banyak terpengaruh. Hamparan seluas 20 juta km2 atau hampir 65 % di Afrika merupakan lahan kering, termasuk wilayah Sahara, Kalahari dan padang rumput di Afrika Timur, di mana sepertiga diantaranya merupakan lahan gurun yang boleh dikatakan tidak berpenghuni. Desertifikasi telah mempengaruhi setidaknya seperlima lahan tanam beririgasi dan tiga per lima lahan tadah hujan di wilayah tersebut.
Di wilayah lain, degradasi lahan juga telah memacu terjadinya migrasi penduduk di Asia Tengah. Di wilayah yang diantaranya mencakup Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan, desertifikasi dan kekeringan telah menyebabkan kerugian tahunan mencapai 6 milyar dolar AS, menyebabkan migrasi sejumlah 2,5 – 4,3 juta orang atau 10 – 15 % populasi yang masih aktif secara ekonomi. Studi di negara-negara tersebut, yang disponsori Badan PBB, mengkonfirmasi bahwa perubahan iklim dalam bentuk kekeringan berkepanjangan telah menyebabkan penurunan produktifitas lahan yang kemudian menyebabkan penurunan penghasilan masyarakat, dan mendorong terjadinya migrasi untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik. Studi juga menyimpulkan bahwa 98 % pendapatan para pelaku migrasi tersebut dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan tidak menyisakan kesempatan untuk menabung dan berinvestasi, apalagi untuk membiayai program tata guna lahan yang berkelanjutan.
Ketahanan terhadap kekeringan adalah tindakan nyata yang harus dilakukan oleh manusia untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Tahun 2023, memberikan pelajaran penting bagaimana warga Makassar harus beradaptasi dengan temaramnya malam, jika listrik tidak menyala. PLN tidak mampu mengatasi kegelapan ini jika ketersediaan air menjadi masalah, Kekeringan terjadi sebagai pengurangan persediaan air atau kelembaban yang bersifat sementara secara signifikan di bawah normal atau volume yang diharapkan untuk jangka waktu khusus. Dampak kekeringan muncul sebagai akibat dari kekurangannya air, atau perbedaan-perbedaan antara permintaan dan persediaan air. Apabila kekeringan sudah mengganggu dampak tata kehidupan, dan perekonomian masyarakat maka kekeringan dapat dikatakan bencana. Bencana yang diakibatkan ini bermacam-macam, yang paling mudah dirasakan adalah terjadinya dehidrasi. Kekeringan bisa saja terjadi bukan karena kurangnya curah hujan saja. Kekeringan yang disebabkan oleh faktor meteorologi misalnya, merupakan ekspresi perbedaan presipitasi dari kondisi normal untuk suatu periode tertentu, karena itu faktor meteorologi bersifat spesifik wilayah. Indonesia merupakan wilayah dengan letak yang sangat unik, apalagi Pulau Sulawesi. Selain dipengaruhi oleh dua iklim, Sulawesi juga dipengaruhi oleh dua gejala alam yaitu gejala alam La Nina yang dapat menimbulkan banjir dan gejala alam El Nino yang menimbulkan dampak musim kemarau yang kering, karena letaknya dipengaruhi oleh Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Indonesia di sebelah selatan. Fenomena El-Nino yang terjadi di Indonesia menyebabkan meningkatnya bencana kekeringan. Kekeringan merupakan ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, dan kebutuhan di sektor lainnya, Penulis, tanggal 28 Maret kemarin, menguraikan di koran ini bagaimana warga Makassar sangat berharap di Kawasan Karst Maros Pangkep di sebelah utara dan Kawasan Malino di sebelah timur. Kedua kawasan ini sangat berperan dalam menjaga kesetimbangan ekosistem di ota Makassar.
Sejatinya, kelestarian lingkungan adalah suatu keniscayaan yang harus dijaga dan dipelihara secara terus menerus. Sehingga, perlu dan harus terus dikumandangkan dengan lantang bahwa bumi, laut dan bahagian yang berada di antara keduanya memerlukan tangan-tangan terampil dan kebijakan cerdas dari pihak yang diberi amanah untuk terus berupaya dengan keras untuk mencari solusi. Untuk itu, perubahan pola prilaku dan pola berpikir memegang peranan penting. Perubahan prilaku mudah dilakukan, karena bisa diamati dan saling mengajak satu sama lain untuk membersihkan diri dari sifat tamak, rakus dan sifat jelek lainnya. Bumi sendiri dapat memenuhi kebutuhan manusia, tetapi tidak dapat memenuhi ketamakan umat manusia. Bumi dapat melakukan keseimbangan diri untuk proses hidup dan kehidupan makhluk hidup lainnya.
Wallahualam bissawab.-
Makassar, Juni 2024.-
| Cegah Stunting, Tim PPK Ormawa HIMA Sosiologi UNM Latih Ibu-ibu Barrang Lompo Buat Nutice Roll |

|
|---|
| Dosen UNM Latih Kelompok Ojek Perahu Rammang-rammang Sport Tourism |

|
|---|
| Kala Senator Senayan Disidang di Seminar Proposal Disertasi di UNM |

|
|---|
| Launching Kampus Kopi di Sinjai, Mahasiswa UNM Gandeng Kawasan Madaya |

|
|---|
| UNM Kukuhkan 24 Insinyur Baru, Prof Andi Aslinda Tegaskan Komitmen Cetak SDM Unggul |

|
|---|







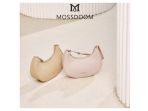






Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.