Opini
Kedaulatan Digital dalam Penyelenggaraan Pemilu
Ketika teknologi dihadirkan sebagai solusi maka diharapkan hadir proses yang lebih efisien, data lebih akurat, dan hasil yang lebih transparan.
Oleh: Endang Sari
Dosen Ilmu Politik FISIP Unhas
TRIBUN-TIMUR.COM - PEMILU di era disrupsi digital seharusnya menjadi tonggak kemajuan dalam tata kelola demokrasi.
Ketika teknologi dihadirkan sebagai solusi maka diharapkan hadir proses yang lebih efisien, data lebih akurat, dan hasil yang lebih transparan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengembangkan berbagai sistem informasi digital dalam beberapa pemilu terakhir.
Di antaranya adalah Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) untuk pengelolaan daftar pemilih, Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) untuk digitalisasi hasil suara, Silon (Sistem Informasi Pencalonan) untuk pengajuan dokumen pencalonan, dan Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) untuk verifikasi partai politik.
Di atas kertas, sistem-sistem ini tampak progressif dan menjanjikan. Namun dalam praktiknya, muncul berbagai persoalan mendasar terkait biaya yang tidak sedikit, efektivitas yang rendah, integrasi yang masih lemah, dan transparansi yang minim.
Permasalahan Sistem Informasi Pemilu
Permasalahan utama terletak pada besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk pengembangan sistem yang tidak berkesinambungan.
Setiap kali pemilu digelar, sistem digital dibuat kembali dari awal tanpa adanya kesinambungan arsitektur teknologi yang matang.
Misalnya, pada Pemilu 2019 digunakan Situng (Sistem Informasi Perhitungan Suara), namun pada 2024 digantikan oleh Sirekap.
Pola pembangunan teknologi ini bersifat temporer dan belum mencerminkan sebuah investasi jangka panjang yang strategis.
Permasalahan kedua menyangkut integrasi antar sistem. Informasi dari Sidalih belum terintegrasi secara langsung dengan Silon, Sipol, maupun Sirekap.
Hal ini menyebabkan pengulangan entri data, ketidaksesuaian informasi, serta meningkatnya beban administratif bagi petugas pemilu di lapangan.
Aplikasi Sirekap KPU Pemilu 2024 misalnya, masih mengalami kendala yang memengaruhi kelancaran proses rekapitulasi suara secara digital yaitu seringnya terjadi kesalahan pembacaan angka pada formulir C1-Plano akibat keterbatasan teknologi OCR yang digunakan.
Hal ini menyebabkan data yang ditampilkan di aplikasi tidak selalu sesuai dengan dokumen fisik.
Selain itu, banyak petugas KPPS di lapangan menghadapi kesulitan teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil, terutama di daerah terpencil.
Beberapa di antaranya juga belum menerima notifikasi aktivasi aplikasi dari KPU, sehingga tidak dapat mengakses sistem untuk mengunggah data. Situasi ini memperlambat proses input dan validasi suara.
Di sisi lain, perubahan tampilan hasil suara di aplikasi, seperti penghapusan grafik perolehan suara dan hanya menampilkan foto formulir C1, menimbulkan kebingungan dan spekulasi di masyarakat.
Ketidaksesuaian antara data digital dan dokumen fisik yang ditemukan oleh publik semakin memperkuat spekulasi tentang adanya potensi manipulasi atau kesalahan sistem.
Permasalahan ketiga terletak pada kurangnya proses audit dan keterbukaan informasi. Masyarakat tidak memiliki akses terhadap rancangan sistem, perlindungan data, maupun laporan audit independen.
Kondisi yang tertutup ini memicu keraguan publik atas validitas data serta efektivitas pemanfaatan anggaran.
Permasalahan keempat adalah ketergantungan pada vendor eksternal. KPU masih belum memiliki struktur teknologi informasi yang kokoh dan bersifat tetap.
Dampaknya, proses pengembangan serta perawatan sistem digital sangat bergantung pada vendor eksternal.
Belum tersedia inisiatif peningkatan kapasitas sumber daya manusia internal yang dapat menjamin kesinambungan dan penguasaan teknologi oleh institusi sendiri.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut efisiensi, melainkan juga menyentuh aspek kedaulatan digital dalam pelaksanaan demokrasi.
Dalam teori tata kelola pemerintahan (governability), seperti yang dikemukakan oleh Pierre dan Peters, efektivitas institusi publik sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan dan integrasi sistem.
Pemerintahan yang baik bukan hanya soal niat baik, tetapi juga soal desain kelembagaan yang mampu menjamin konsistensi, akuntabilitas, dan adaptabilitas.
Dalam konteks ini, sistem informasi pemilu yang terfragmentasi dan tidak berkelanjutan mencerminkan lemahnya tata kelola digital dalam penyelenggaraan pemilu.
Lebih jauh, teori legitimasi demokrasi dari David Beetham menekankan bahwa legitimasi tidak hanya berasal dari prosedur hukum, tetapi juga dari kepercayaan publik terhadap proses.
Ketika sistem digital pemilu tidak transparan, sering error, dan tidak dapat diaudit secara independen, maka legitimasi hasil pemilu pun bisa dipertanyakan. Dalam demokrasi, persepsi publik sama pentingnya dengan prosedur formal.
Masukan Perbaikan di Revisi Undang-Undang Pemilu
Untuk menjawab tantangan ini, revisi Undang-Undang Pemiu menjadi langkah mendesak.
Pertama, UU harus memastikan bahwa semua sistem informasi pemilu dirancang secara terpadu, berkesinambungan, dan tidak lagi bergantung pada proyek sementara.
Dibutuhkan konsolidasi digital pemilu nasional yang menggabungkan seluruh sistem mulai dari data pemilih, proses pencalonan, partai politik, sampai rekap hasil dan laporan dana kampanye dalam satu ekosistem yang saling terhubung.
Kedua, Undang-undang perlu menetapkan kewajiban audit independen secara rutin terhadap semua sistem teknologi pemilu.
Proses audit ini meliputi aspek keamanan digital, efektivitas, stabilitas teknis, serta fungsi sistem.
Laporan hasil audit wajib diumumkan secara transparan, agar masyarakat, komunitas teknologi, dan pengawas pemilu bisa ikut serta dalam proses pengawasan dan peningkatan.
Ketiga, KPU sebaiknya mendirikan unit tetap bidang teknologi informasi di level nasional dan regional, yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dengan kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Pengembangan sistem digital idealnya dilakukan secara mandiri, atau lewat kerja sama berkelanjutan dengan institusi teknologi pemerintah seperti BRIN, BSSN, dan Kominfo, demi memastikan kendali serta kesinambungan.
Keempat, Semua sistem digital seperti Sirekap, Sidalih, Silon, dan Sipol sebaiknya digabungkan dalam satu laman nasional pemilu yang menyediakan akses masuk terpadu, tampilan yang mudah digunakan, serta panel informasi publik yang transparan.
Strategi ini bukan hanya memudahkan petugas dan kontestan pemilu, tetapi juga meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap keterbukaan dan kelancaran proses digital pemilu.
Pembangunan sistem informasi pemilu bukan sekadar proyek teknologi, tetapi bagian dari kedaulatan digital infrastruktur demokrasi.
Sistem ini harus dirancang dengan visi jangka panjang, dikelola secara profesional, dan diawasi secara terbuka.
Demokrasi digital yang sehat membutuhkan sistem yang tidak hanya canggih, tetapi juga dapat dipercaya.
Dan kepercayaan itu hanya bisa tumbuh jika teknologi dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik, bukan sekadar logika temporer.
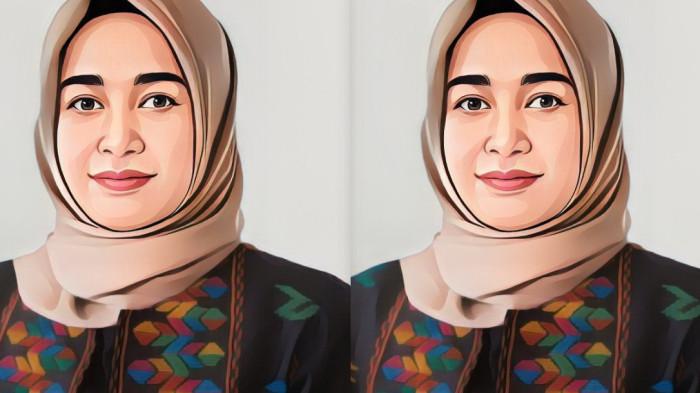





















Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.