Opini Aswar Hasan
Urgensi Teks dan Konteks Secara Proporsional dalam Memahami Agama
Setelah mendengar sabda tersebut, para sahabat berangkat menuju Bani Quraizah.
Oleh: Aswar Hasan
Dosen Fisipol Unhas
TRIBUN-TIMUR.COM - Sebuah tulisan yang mencerahkan dari Prof Ahmad M Sewang yang beredar di goup WA ICMI membuat saya merasa perlu menanggapinya.
Tulisan tersebut berangkat dari hadis menyangkut peristiwa Bani Quraizah, sebuah perkampungan komunitas Yahudi di Madinah, pada saat “Nabi saw. bersabda sekitar Perang al-Ahzab: “Janganlah seseorang melaksanakan salat Asar kecuali setelah tiba di perkampungan Bani Quraizah.”
Setelah mendengar sabda tersebut, para sahabat berangkat menuju Bani Quraizah. Namun, di tengah perjalanan, waktu salat Asar sudah hampir habis. Di sinilah timbul dua pemahaman di antara mereka:
1. Sebagian sahabat memahami hadis itu secara kontekstual dan melaksanakan salat Asar dalam perjalanan, karena waktu salat sudah tiba.
2. Sebagian yang lain memahami hadis itu secara tekstual, sehingga mereka berkata tidak akan melaksanakan salat Asar hingga tiba di Bani Quraizah berdasarkan sabda Nabi, meskipun waktu salat Ashar telah berakhir.
Ketika kejadian itu dilaporkan kepada Nabi saw., beliau tidak menyalahkan salah satu pihak. Hal ini menunjukkan fleksibilitas Nabi saw. dalam memahami pandangan para sahabat, baik melalui metode tekstual maupun kontekstual.
Prof. Ahmad M Sewang mengutip pandangan Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama kontemporer, yang menegaskan bahwa memahami sunnah tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial penuturan hadis.
Menurut beliau, memahami sunnah harus mempertimbangkan tujuan (maqasid), konteks sosial (mulabasat), dan sebab-sebab tertentu (asbab).
Dengan pendekatan ini, kita dapat memahami apakah isi sebuah hadis bersifat universal atau bersifat temporal (terbatas pada waktu dan tempat tertentu).
Beliau lalu menyimpulkan bahwa hadis di atas menunjukkan bahwa metode tekstual dan kontekstual sama-sama valid dalam memahami sebuah hadis.
Meskipun kedua metode tersebut dapat digunakan, umat Islam harus cerdas memilih pendekatan yang lebih maslahat dan relevan dengan perkembangan zaman.
Dalam memahami hadis, teks dan konteks sebaiknya saling bersinergi.
Mengandalkan teks tanpa konteks akan menghasilkan pemahaman yang kaku (rigid), sedangkan mengutamakan konteks tanpa memperhatikan teks akan menjurus pada pandangan liberal.
Sepenuhnya, kesimpulan pendapat beliau (guru saya) saya sependapat dengan catatan bahwa tidak semua teks agama harus dikontekstualisasi. Sebaliknya, memahami agama secara tekstual semata juga harus dihindari.
Bahaya Kontektualisasi
Jika semua teks agama dikontekstualisasikan tanpa panduan metodologis yang jelas, tafsir agama dapat menjadi liar dan tidak terkendali.
Setiap orang dapat memberikan interpretasi yang sesuai dengan pemahamannya sendiri, tanpa mempertimbangkan landasan keilmuan atau kesepakatan ulama.
Menyebabkan berkembangnya faham dekonstruksi sebagai ekses faham liberalisme yang mengakibatkan terjadinya anarki tafsir dalam memahami teks agama.
“Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat.” (QS. Al-Baqarah: 43) Adalah contoh ayat tekstual yang tak memerlukan kontekstualisasi.
Perintah ini sering dipahami secara harfiah tanpa memerlukan konteks apalagi dekonstruksi, karena salat dan zakat adalah kewajiban yang sudah jelas tata caranya dalam Islam.
Jacques-Marie Émile Derrida adalah bapak deconstruction (dekonstruksi). Ia berpendapat bahwa makna teks selalu bersifat cair, kontekstual, dan terbuka untuk berbagai interpretasi.
Dalam konteks agama, pendekatan ini dapat menyebabkan pandangan bahwa teks agama hanya relevan dalam konteks historisnya dan tidak memiliki keabadian makna.
Dengan kata lain bebas untuk kontekstualisasi demi pemaknaan yang terbuka.
Pandangan Derrida diadaptasi oleh beberapa cendekiawan Muslim kontemporer yang banyak dianut termasuk di Indonesia.
Dalam menafsirkan ulang Al-Qur’an dan hadis, sering kali dengan mengabaikan makna literal atau tradisionalnya.
Seperti yang dilakukan Nasr Hamid Abu Zaid Seorang pemikir Mesir yang menekankan bahwa teks agama memiliki dimensi historis dan harus dipahami sesuai konteks sosial-politik ketika teks itu diturunkan.
Pendekatan tersebut, menuai kritik karena dianggap mendekonstruksi makna sakral teks agama.
Selain Nasr Hamid Abu Zaid ada Mohammed Arkoun Pemikir asal Aljazair yang juga mengkritik tafsir tradisional dan mendorong pendekatan rasional terhadap teks agama.
Arkoun sering dikaitkan dengan pendekatan liberal karena cenderung menganggap teks agama sebagai produk sejarah.
Ada juga Hasan Hanafi. Seorang pemikir Mesir yang mempromosikan hermeneutika dalam memahami Islam.
Ia menekankan subjektivitas dalam memahami teks agama, yang oleh beberapa kritikus dianggap membuka potensi anarki tafsir.
Pendekatan tersebut, jika tidak diimbangi dengan panduan metodologis yang jelas, dapat menimbulkan potensi yang berbahaya seperti dekonstruksi makna asli teks, liberalisme ekstrem, atau anarki tafsir.
Namun demikian tokoh-tokoh tersebut juga memberikan kontribusi besar dalam memperkaya diskursus agama, asalkan pendekatan mereka diterapkan dengan penuh kehati-hatian dan tetap merujuk pada maqasid syariah berdasarkan tradisi keilmuan Islam.
Olehnya itu, kontekstualisasi ajaran Islam meskipun dianggap metode penting untuk menjawab tantangan zaman sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar agama, harus dilakukan dengan hati-hati, sebab pendekatan ini dapat disalahpahami sebagai liberalisasi atau sekularisasi.
Serba Tekstual Memundurkan Islam
Sebaliknya, pandangan yang fokus pada tekstualisasi atau skriptualisasi dalam memahami Islam juga dapat menimbulkan berbagai kerugian pemahaman agama secara menyeluruh.
Diantaranya, terjadi Kekakuan (Rigidity) dalam memahami ajaran Islam.
Pemahaman Islam yang hanya berfokus pada teks secara literal tanpa mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan historis bisa menyebabkan interpretasi yang kaku dan tidak fleksibel.
Bahwa Islam memiliki tujuan utama (maqasid syariah) yang mencakup keadilan, kesejahteraan umat, perlindungan hak-hak individu, dan kemaslahatan umat.
Pemahaman yang hanya mengandalkan teks literal sering kali mengabaikan tujuan-tujuan tersebut karena teks-teks agama dipahami dengan cara yang sempit dan tidak mempertimbangkan maslahat (kebaikan) yang lebih besar.
Akibatnya, umat Islam hanya fokus pada formalitas agama dan kehilangan kedalaman spiritual yang menjadi inti dari ibadah atau ajaran Islam itu sendiri.
Pemahaman yang terlampau tekstual dan literal terhadap teks agama sering kali digunakan oleh kelompok radikal untuk membenarkan tindakan kekerasan atau ekstrim mereka.
Bahaya kelompok-kelompok ini mungkin mengabaikan konteks sosial, sejarah, dan tujuan ajaran Islam dalam upaya mereka untuk menegakkan versi pemahaman mereka sendiri dari hukum Islam.
Hal ini dapat memicu kekerasan, intoleransi, dan ekstremisme, yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai utama Islam, seperti kasih sayang, perdamaian, dan keadilan.
Pandangan yang terlalu tekstual dalam memahami Islam berimplikasi dalam pemahaman ajaran agama yang kehilangan pada tujuan-tujuan syariat yang lebih besar.
Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pendekatan yang lebih mensinergikan pemahaman literal dengan konteks sosial dan sejarah, agar ajaran Islam tetap relevan, fleksibel, dan dapat memberikan maslahat bagi umat di setiap tempat dan zaman. Wallahu a’lam bisawwabe.(*)



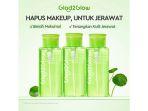














Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.