Opini
Irasionalitas Politik dan Matinya Kebenaran
Dalam memenangkan kontestasi, para politisi senang menebarkan misinformasi, pernyataan retoris dan klaim tanpa bukti.
Oleh: Muhajir MA
Koordinator Paguyuban Ekosistem Informasi Sehat (PESAT) Sulsel
Sejak dulu politik selalu menjadi arena yang penuh kebohongan.
Namun saat ini, politik tak hanya ajang dalam mengedarkan dusta, melainkan juga menjadi panggung bagi matinya kebenaran.
Dalam memenangkan kontestasi, para politisi senang menebarkan misinformasi, pernyataan retoris dan klaim tanpa bukti.
Semua itu dilakukan bukan untuk menyampaikan kebenaran, tapi sekadar menyatakan pembenaran.
Mereka tidak berupaya menyampaikan fakta, melainkan menciptakan "fakta alternatif".
Bagi banyak politisi, tak penting informasi tersebut benar atau salah.
Yang penting adalah segala sesuatu tetap sejalan dengan keinginan dan keyakinan pribadinya.
Karena setiap politisi ingin terlihat mendominasi dan tidak tergoyahkan, agar bisa merebut kepercayaan publik, meski harus berbohong dan melecehkan kebenaran.
Inilah yang saya sebut sebagai irasionalitas politik.
Wajah politik yang "di luar nalar" tersebut semakin mempertegas jika kita belum bisa melepaskan diri dari warisan
budaya politik pasca-kebenaran (post-truth).
Oxford Dictionaries mendefinisikan pasca-kebenaran sebagai istilah yang merujuk keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan ajakan emosional dan keyakinan pribadi.
Era yang juga disebut sebagai pasca-faktual (post-factual) ini mengubah ungkapan “I think therefore I am” menjadi “I believe therefore I’m right”.
Kecenderungan irasional tersebut sudah marak ditemui di Pemilu 2024.
Misalnya baru-baru ini dalam kampanyenya, Prabowo memainkan retorika hiperbolik dengan menuduh mereka yang menakuti rakyat sebagai antek asing. Tidak jelas siapa yang dimaksud sebagai "mereka" yang antek asing.
Pernyataan spekulatif itu disampaikan begitu saja tanpa konteks.
Ada juga klaim Ganjar Pranowo tentang elektabilitasnya yang masih baik berdasarkan survei internal, meskipun sejumlah lembaga survei menunjukkan sebaliknya.
Hal paling tak masuk akal ketika politikus Roy Suryo menuduh Gibran menggunakan mikrofon khusus agar dapat didikte dari jauh selama debat cawapres.
Nyatanya, Kominfo dan sejumlah lembaga cek fakta telah memverifikasi jika tiga cawapres saat itu menggunakan mikrofon yang sama dengan jumlah yang sama.
KPU juga sudah menyatakan klaim tersebut sebagai hoaks.
Bukannya bertobat, Roy Suryo malah ngotot merasa dirinya benar dan melaporkan Ketua KPU ke polisi.
Semua pernyataan tersebut jelas irasional. Karena tidak didasari oleh kebenaran objektif dan bukti yang kuat.
Tapi hanya sekadar ungkapan perasaan dan pembenaran yang selaras dengan keyakinan pribadinya.
Pertanyaannya, mengapa klaim seperti itu tanpa ragu disampaikan oleh para politisi?
Bisa dipastikan perbuatan tersebut bukan hanya sekadar iseng dan sinisme belaka.
Para politisi adalah spin doctor dengan niat yang jelas: memengaruhi opini publik.
Pasca-kebenaran, kata Lee McIntyre (2018) adalah supremasi ideologis di mana para praktisinya mencoba memaksa seseorang untuk percaya pada sesuatu terlepas ada bukti atau tidak.
Pemaksaan keyakinan tersebut tentu mudah dilakukan jika publik punya kecederungan untuk menerima gagasan yang sesuai dengan perasaan dan keyakinan pribadinya.
Sadar atau tidak, kita semua punya kecondongan seperti itu.
Selama beberapa dekade, para psikolog telah melakukan eksperimen yang menunjukkan bahwa manusia tidak selalu serasional yang diperkirakan.
Dalam diri manusia tertanam apa yang McIntyre sebut sebagai bias kognitif, yang menjadi akar terdalam dari fenomena pasca-kebenaran.
Salah satu temuan klasik psikologi sosial telah menjelaskan bahwa manusia memiliki bias kognitif yang disebut
sebagai disonansi kognitif.
Teori ini menjelaskan jika manusia cenderung mencari keselarasan antara keyakinan, sikap, dan perilakunya, dan mengalami ketidaknyamanan psikis jika elemen-elemen ini tidak sejalan.
Untuk mengurangi disonansi kognitif, orang-orang cenderung mengubah atau membenarkan salah satu komponen yang bertentangan.
Misalnya mengubah perilakunya agar sesuai dengan keyakinan yang dimilikinya.
Atau mencari pembenaran dengan mendukung argumen yang sesuai keyakinan mereka.
Maka dari itu, inti dari pasca-kebenaran bukan hanya tentang kebohongan, tapi bagaimana suatu informasi dipilih dan disajikan sesuai dengan pandangan pribadi orang-orang.
Bahkan ketika kebohongan digunakan untuk memanipulasi opini publik, tindakan tersebut tak bisa dianggap remeh.
Sebab tendensi kebohongan dalam pasca-kebenaran lebih berbahaya dibandingkan kebohongan biasa.
Vittorio Bufacchi (2020) mengatakan, inti dari kebohongan adalah bahwa si pembohong mengakui adanya kebenaran, namun memilih untuk menyampaikan kisah yang berbeda.
Sementara di era pasca-kebenaran si pembohong tidak hanya menyangkal fakta, melainkan juga bertujuan untuk meruntuhkan
infrastruktur teoretis yang mendasari kemungkinan membicarakan kebenaran.
Masih segar di ingatan ketika Donald Trump menuduh Tiongkok menciptakan konsep pemanasan global untuk menjadikan manufaktur AS tidak kompetitif.
Atau, pada Pilpres 2019 lalu, di mana Prabowo mengklaim kemenangannya.
Padahal baik hasil hitungan cepat KPU dan beberapa lembaga survei telah mengumumkan kemenangan Jokowi-Ma’ruf.
Baik Trump maupun Prabowo secara sadar membuat orang-orang meragukan kredibilitas sains dengan cara menyangkal fakta.
Di era pasca-kebenaran seorang politisi bisa saja meruntuhkan keandalan sumber-sumber epistemik terpercaya dengan merumuskan “fakta alternatif”, jika kebenaran mengancam dirinya.
Dengan kata lain, kebenaran telah diremehkan dan dianggap tidak relevan lagi.
Hal tersebut sama halnya membunyikan lonceng kematian bagi kebenaran.
Lantas adakah jalan keluar dari pasca-kebenaran? Dengan berat hati saya mengatakan, tidak ada.
Pasca-kebenaran tidak akan pernah hilang. Jika ada ruang bagi kebenaran menyelinap masuk dalam arena politik, maka akan selalu ada seseorang yang siap mempromosikan pasca-kebenaran.
Meski demikian, setidaknya kita bisa meminimalkan pengaruh negatifnya.
Di sini, dibutuhkan peran lembaga pendidikan dalam menumbuhkan pemikiran kritis dan kesetiaan pada fakta.
Kita juga membutuhkan peran lembaga independen untuk menyelenggarakan literasi digital secara masif, kesediaan masyarakat untuk bermedia sosial secara cakap, dan kesungguhan media massa dalam menebarkan kebenaran dan memeriksa fakta.
Tak kalah pentingnya, kita memerlukan kejujuran dan kebijaksanaan para politisi dalam berkompetisi.
Tapi, apakah mungkin itu terjadi? Entahlah. Saya lantas teringat pernyataan Hannah Arendt (1967), bahwa politik dan kebenaran tidak bisa dicampuradukkan.
Karena tak ada satu pun orang yang menganggap kejujuran sebagai bagian dari kebajikan politik.

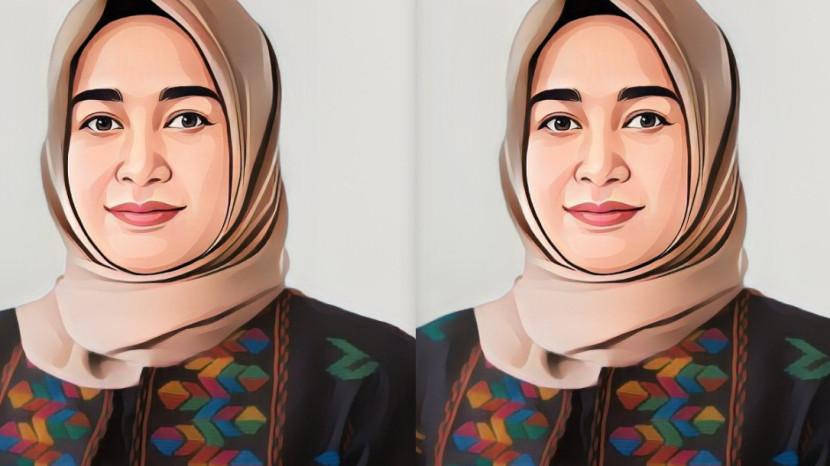


















Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.