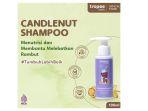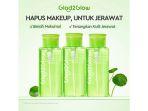Opini
Hak Demokrasi dalam Kolom Pemilu dan Tantangannya
Belajar dari riwayat pemilu masa lalu, nampaklah proses demokrasi sedang berbenah, mengubah wajahnya dari masa ke masa.
Oleh:
Juanto Avol
Komisioner Bawaslu Gowa
TRIBUN-TIMUR.COM - Pena sejarah mencatat, pemilihan umum di tanah air kali pertama dilakukan 1955 sebagai wajah demokrasi terpimpin.
Enam belas tahun kemudian sistem parlementer proporsional itu ditanggalkan.
Setelahnya, dari hasil pemilu berikutnya lahirlah ‘kekuasaan’ Orde Baru.
Sistem kepemiluan era orde baru memang nampak demokratis tapi berasa monokrasi.
Rezim itu kemudian ‘berselimut’ teori demokrasi Abraham Lincoln yang terus digaungkan atas nama rakyat, dari rakyat untuk rakyat.
Faktanya kemudian terasa berbeda, tunas otoritearisme justeru mulai tumbuh sebagai cikal bakal kekuasaan terlama dalam sejarah kepemimpinan Indonesia.
Membahas tentang kedua rezim diatas perlu kehati-hatian agar tak terjadi distorsi sejarah.
Hal itu cukuplah sebagai produk ‘usang’ di masanya, hingga gejolak reformasi 1998-1999 digaungkan.
Sebagai pemantik braindstorming, lima puluh satu tahun silam (1971), ada sekelompok anak muda kaum terpelajar dan rakyat, tersadar tentang pentingnya perubahan dalam sistem kepemiluan.
Mereka mendamba sebuah pemilihan kepemimpinan yang terbuka, adil, jujur, dan rahasia. Semangatnya, agar sejalan dengan slogan tadi, dari rakyat untuk rakyat.
Pemikiran kritis itu 1971 akhirnya melahirkan sebuah gerakan moral, murni yang diinisiatori oleh mereka, kemudian menjelma dan menyebar istilah Golput (golongan putih) yang mempengaruhi wajah demokrasi selanjutnya.
Pada momentum lain dalam dialog publik, di salah satu stasiun TV lokal 2018, timbul pertanyaan, apa itu Golput.
Benarkah ia wujud suci politik tanpa pilihan atau sebagai sebuah gerakan perlawanan karena tak ada pilihan lain? Ini yang menarik.
Menanggapi tanya diatas, konon dalam konteks Pemilu Orba, jika rakyat tak tertarik dengan calon atau tokoh tertentu, maka mereka yang berpikir kritis, lebih tergugah memilih Golput.
Golput kala itu, boleh jadi sebagai ruang ekspresi, representasi rakyat secara objektif, sebuah pilihan untuk tidak berpartisipatif.
Bila perlu, berdiam di rumah, pergi berkebun atau duduk menikmati secangkir kopi dengan kepulan asap tembakau.
Begitulah kira-kira cara sederhana rakyat melakukan perlawanan politik dimasa lalu, pada pemangku kepentingan yang tidak mengakomodatif aspirasi rakyat.
Bila melihat konteks demikian dalam kacamata demokrasi kini, sepertinya gambaran proses itu macet, tidak hanya ‘dibajak’ tapi juga gersang makna kebebasan berpendapat dan berekspresi, terkekang dalam ketidakadaan sistem dan regulasi pemilihan yang tepat.
Bisa dimaknai, pengaruh kekuasaan saat itu punya kendali (memaksa) terhadap partisipasi pemilih.
Rakyat kemudian terjerambak untuk tidak menyalurkan haknya, atau memilih tapi vacum, dan berada dalam tekanan aktor politik yang melanggeng tanpa hambatan.
Wajah pemilu seperti itu cukup suram, bila dikritik akan muncul argumentasi-argumentasi politik bahwa proses pemilihan sudah sesuai, meski dibungkus atas nama rakyat.
Argumentasi diatas mungkin hanya upaya pembenaran, untuk meligitimasi adanya pemilihan umum, namun sistematika dan tata caranya ‘menjerat’ rakyat, tak bersuara murni atas pilihannya sendiri.
Sehingga yang nampak justeru ketakutan dari sebuah kuasa kekuatan besar yang sulit untuk dilawan.
Saking kuatnya, ia langgeng selama tiga dekade dengan sentralistik kontrol atas kendali segala sumberdaya yang ada.
Ironinya, bila dikritik, kebebasan bisa lenyap bak embun panas dipagi hari.
Kolom Sah
Belajar dari riwayat pemilu masa lalu, nampaklah proses demokrasi sedang berbenah, mengubah wajahnya dari masa ke masa.
Sistem kepemiluan dan regulasinya terus beradaptasi, berorientasi pada perwujudan pemilu yang partisipatif, representatif, berintegritas dan bermartabat yang dilengkapi ‘rul of law and rul of ethics’.
Hal itu terus berlangsung diperjuangkan di berbagai wilayah Indonesia.
Gambaran proses pemilu serentak 2024 mendatang, kini telah memasuki tahapan awal yang sedang berlangsung, yaitu verifikasi administrasi Parpol sebagai calon peserta pemilu.
Sistem itu merupakan cerminan karakter demokrasi terbuka, walau mungkin masih dalam keterbatasan prangkat verifikasi dan bayang masa lalu.
Ada dua indikator gambaran itu terasa nampak, ketika parpol tidak siap dengan segala perangkatnya, hingga ditemukan dan dilaporkan beberapa diantaranya mencatut nama-nama warga ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang bukan anggota dan pengurus Parpol.
Kedua, bila melihat Pemilihan-pemilihan sebelumnya, mungkin Parpol ‘kering’ melahirkan kader-kader berkualitas sebagai calon-calon pemimpin yang disodorkan kepada konstituen, sehingga diperhadapkan dengan potensi Kolom kosong (Koko).
Sebenarnya “mahluk Koko” ini, bukanlah hal baru, sungguh bukan.
Loncatan ingatan yang dikemukakan tadi soal Golput, sebuah tranformasi pemikiran gerakan ke kolom kosong, sebut saja begitu.
Sebab konon, Golput dimaknai gerakan perlawanan, kritik rakyat terhadap pemimpin otoriter dan atau tokoh tertentu.
Maka pemaknaan kolom kosong kali ini, juga bisa ditelaah sebagai tempat ‘memilih untuk tidak memilih’.
Apa itu ‘memilih untuk tidak memilih’? Bisa dikatakan, hanya istilah dan zamannya berbeda.
Orde baru berubah ke reformasi-demokrasi, Golput bertransformasi ke kolom kosong.
Bedanya dimana? Golput dahulu dalam konteks orde baru, tak diatur sebagai hak konstitusional, jika tak memilih, suara dianggap tidak ada, ‘hangus’.
Sedangkan kolom kosong dalam wajah demokrasi sekarang, diatur dalam regulasi kepemiluan sebagai ruang hak konstitusional, sah.
Berdasarkan nomenklatur pasal 14 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), nomor 13 tahun 2018. Lalu dimana titik temunya?
Apapun istilahnya, mau dia Golput atau kolom kosong, ia merupakan wadah representasi rakyat, bisa ‘memilih untuk tidak memilih calon’.
Hal ini pula dimaknai, rakyat memilih untuk tidak memilih orang, partai dan nomor urut. Sehingga menyalurkan hak suaranya ke kolom kosong.
Atau sebaliknya, rakyat ‘memilih untuk tidak memilih kolom kosong’, lalu menyalurkan hak suaranya ke kolom calon beserta partai dan nomor urutnya.
Yang pasti, kedua hal diatas diakomodir sebagai hak ruang partisipatif.
Ketika kritik muncul, siapa yang bisa menduga adanya suara rakyat dalam kolom kosong sebagai gerakan kritis, wujud perlawanan, representasi ketidakberpihakan mereka pada calon tertentu?
Mungkin satu hal yang patut dipahami, bahwa kolom kosong bukanlah sekadar kotak kardus, hampa tanpa suara.
Melihatnya di dalam sana, perlu dengan nalar demokrasi sehat, ada subjektivitas dan objektivitas.
Misalnya objektifitasnya didasari kekecewaan yang mereka (rakyat) alami. Rasa ketidakadilan, kesenjangan sosial, kemiskinan, ketertinggalan pembangunan, sulitnya lapangan kerja, lambannya layanan kesehatan dan lain sebagainya.
Sederhana pandangan ini dianalogikan, calon melawan kolom kosong atau kolom kosong melawan calon, boleh.
Sungguh itu bisa dimaknai ‘head to head’ dengan rakyat, karena dalam regulasi kepemiluan, itu sah.
Kalau ditanya, calon dekat rakyat yang mana, atau rakyat dukung calon siapa dan sebaliknya?
Jawabnya dalam posisi logis tadi, ialah rakyat yang memiliki hak pilih untuk menyalurkan suaranya di kolom kosong atau kolom calon.
Tentu kompleksitasnya ada pro dan kontra, itu kebebasan dalam control, lumrah. Jika mengamati forum-forum rakyat di sudut kota, pelosok kampung, warung kopi dan media sosial.
Diskusi-diskusi kepemiluan tentang kolom kosong tak pernah alpa dari pertanyaan, apakah hal itu berpotensi kecurangan?
Misalnya warga pro kolom kosong ditunggangi, disemangati memilih atas fakta-fakta kekecewaan tadi, entah.
Rakyat berharap pemilu mendatang, sejatinya murni didorong bersama tanpa ditunggangi kepentingan-kepentingan ‘kotor’ seperti hoax, politik identitas (SARA), intervensi kebijakan dan politik uang.
Sebab sadar atau tidak, jika politik demikian dilakoni, maka prilaku tak elok itu bagai warisan gelap ‘lingkaran setan’.
Mereka bak memberi namun kasat mata merampas banyak hak-hak rakyat. Sebuah jalan kelam menuju kemunduran bangsa yang jauh dari akal sehat. (*)