Opini
Siapa Penemu Benua Australia? James Cook atau Pelaut Makassar?
Kebanyakan sejarawan memulai kisah mereka dari catatan Eropa — arsip VOC, jurnal kolonial, dan peta Inggris.
Siapa Penemu Benua Australia? James Cook atau Pelaut Makassar?
Penulis : Saparuddin Santa
Peneliti dan Penulis Independen dari Makassar, Indonesia
“Ketika matahari sedang terbit dari Timur, kami Pelaut Makassar sedang mengayuh Perahu kami, melintasi Laut Timur dan Laut Arafuru menuju Daratan Australia; kamilah yang menemukanmu.” Tradisi Lisan Pelaut Makassar, Sulawesi Selatan
Saya tumbuh dengan cerita-cerita yang tak tercatat di buku sejarah.
Orang-orang tua di Makassar bercerita tentang pelaut pemberani yang menembus cakrawala, menuju tanah yang mereka sebut Marege’ pesisir yang kini dikenal sebagai Australia bagian utara.
Cerita itu diwariskan turun-temurun bukan sebagai legenda, melainkan sebagai memori hidup tentang jati diri dan kebanggaan sebuah bangsa pelaut.
Namun ketika saya mulai membaca buku-buku sejarah Australia, saya terkejut menemukan betapa sunyinya suara dari seberang laut itu.
Kebanyakan sejarawan memulai kisah mereka dari catatan Eropa — arsip VOC, jurnal kolonial, dan peta Inggris.
Seolah-olah sejarah baru dimulai ketika orang Eropa menulisnya.
Padahal jauh sebelum James Cook menjejakkan kaki di pantai timur Australia pada 1770, pelaut- pelaut Makassar telah lebih dulu berlayar ke utara benua itu untuk mencari teripang dan tinggal bersama masyarakat Aborigin di Arnhem Land dan Pulau Kimberley.
Bahkan para pelaut Makassar melakukan perkawinan dengan penduduk setempat, yang kemudian melahirkan keturunan yang masih hidup hingga hari ini.
Kisah itu bukan sekadar cerita rakyat. Dalam Dreamtime Voyagers, penulis Australia Mike Dash menulis bahwa pedagang Makassar telah menjadi bagian dari jaringan besar dunia maritim sejak abad ke-16.
Ia bahkan mengutip catatan yang menyebut bahwa pada tahun 1650-an, Kerajaan Gowa adalah negara merdeka paling kuat di kepulauan Hindia — dengan jalur pelayaran yang terbentang dari Malaya (Semenanjung Melayu) hingga Cina.
Artinya, jauh sebelum Belanda menancapkan kekuasaan, pelaut Makassar telah membangun hubungan ekonomi dan kultural dengan dunia sekitarnya, termasuk Australia Utara.
Bagi saya, kalimat kecil itu membuka cakrawala baru: bahwa sejarah hubungan Indonesia–Australia tidak dimulai dari kolonialisme, melainkan dari pertukaran kemanusiaan.
Dari sanalah riset ini bermula — di ruang di antara apa yang diingat oleh rakyat dan apa yang dicatat oleh arsip kolonial.
Menghidupkan Kisah-Kisah Tidak Terekam Sejarah
Penelitian ini tidak hanya bertujuan membuktikan siapa yang pertama kali tiba di Australia, tetapi untuk menghidupkan kembali dimensi kemanusiaan dari perjumpaan dua bangsa di tepi Laut Arafuru.
Saya memadukan cerita lisan, catatan VOC, dan pendekatan etnografi kreatif sebagai cara baru membaca sejarah yang selama ini diam dalam arsip.
Pendekatan ini menolak dikotomi antara ilmiah dan kultural.
Cerita rakyat, lagu-lagu pelaut, dan simbol dalam bahasa Yolngu di Arnhem Land yang menyebut “Makassan” dalam kosakata mereka, menjadi bagian dari teks sejarah yang hidup.
Bagi saya, setiap memori masyarakat adalah arsip moral, dan setiap pertemuan antarmanusia adalah bagian dari catatan sejarah yang sah.
Riset ini lahir dari kolaborasi antara peneliti Indonesia dan Australia.
Di pihak Indonesia, dukungan datang dari Jurusan Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, bersama Ishaq Rahman, Ph.D (Candidate) dan Associate Professor Dr. Sudirman Nasir, Ph.D, seorang akademisi di bidang kesehatan internasional dan alumnus Universitas Melbourne.
Sementara dari Australia, dukungan datang dari Professor Hans Pols dari University of Sydney, sejarawan yang telah meneliti hubungan Belanda–Asia Pasifik selama tiga dekade.
Penelitian ini juga mendapat bimbingan Professor Emeritus Stephen Hill dari University of Wollongong, yang memperkenalkan konsep Stand in Humanity, pandangan bahwa hubungan lintas bangsa harus berdiri di atas dasar kemanusiaan bersama, bukan kepentingan geopolitik semata.
Bersama para mentor ini, saya tidak hanya belajar tentang arsip dan teori, tetapi juga tentang kerendahan hati dalam membaca sejarah orang lain.
Sejarah, bagi saya, bukanlah ruang untuk menentukan siapa yang lebih dahulu, tetapi ruang untuk memahami bagaimana manusia saling menemukan.
Menemukan Jati Diri Makassar di Laut yang Sama
Kisah pelaut Makassar dan masyarakat Aborigin adalah kisah tentang dialog tanpa kolonialisme.
Tidak ada kapal perang, tidak ada penjajahan — hanya pertukaran barang, bahasa, dan rasa ingin tahu.
Jejak perahu Makassar masih terlihat di lukisan batu Arnhem Land, dan dalam bahasa lokal mereka, kata balanda (untuk orang kulit putih) berasal dari istilah Makassar untuk Belanda.
Kata-kata itu menjadi bukti bahwa bahasa bisa berlayar lebih jauh daripada kapal.
Bagi saya, ini bukan hanya soal sejarah perdagangan, tetapi tentang hubungan antarmanusia yang lahir dari laut.
Laut Arafuru bukan batas, melainkan jembatan — ruang di mana identitas tidak ditentukan oleh daratan, melainkan oleh perjalanan.
Membangun Kemanusiaan yang Sama di Era Modern
Melalui riset ini, saya mencoba membangun kembali semangat yang pernah hidup di masa para pelaut Makassar: semangat menjelajah, bertukar, dan memahami.
Konsep Shared Humanity. kemanusiaan bersama menjadi inti gagasan saya.
Sebagai peneliti, saya ingin menegaskan bahwa hubungan antarbangsa tidak hanya dibangun di atas diplomasi dan ekonomi, tetapi di atas rasa saling menghormati dan pengakuan akan sejarah bersama.
Dari pemikiran ini, lahirlah gagasan untuk mendirikan Makassar–Arnhem Land Fellowship and Foundation, sebuah platform riset dan pertukaran budaya jangka panjang antara Indonesia dan Australia.
Fellowship ini diharapkan menjadi wadah bagi peneliti muda, penulis, dan komunitas lokal untuk melanjutkan dialog kemanusiaan lintas samudra yang telah dimulai oleh para pelaut berabad-abad lalu.
Sejarah bukan hanya tentang masa lalu.
Ia adalah cermin masa depan, tentang bagaimana kita memilih membaca dan memaknai pertemuan yang telah terjadi.
Dan di Laut Arafuru tempat di mana Makassar dan Marege’ pernah saling memandang, kita belajar bahwa perbatasan sesungguhnya hanyalah garis di peta, bukan di hati manusia.
Tulisan ini disusun sebagai bagian dari persiapan riset sejarah dan kemanusiaan dengan judul:
“Encouraging Shared Humanity: Tracing the Makassar–Aboriginal Connection through Storytelling, Cultural Memory, and Economic Futures.”
Selamat Ulang Tahun Kota Makassar yang ke-418, Ewako!.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/TRIBUN-OPINI-Saparuddin-Santa-Peneliti-dan-Penulis.jpg)





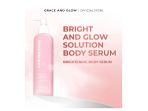














Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.