Opini Alem Febri Sonni
Menjaga Api Kebebasan Pers di Tengah Intimidasi: Refleksi Atas Teror Terhadap Tempo
Peristiwa ini bukan sekadar kasus kriminal biasa, melainkan sebuah serangan terhadap salah satu pilar demokrasi kita: kebebasan pers.
Oleh: Dr. Alem Febri Sonni
Pakar Ilmu Komunikasi, Pengurus ISKI Pusat
TRIBUN-TIMUR.COM - Beberapa hari yang lalu, kita dikejutkan dengan peristiwa yang sangat memprihatinkan dimana kantor redaksi majalah berita mingguan Tempo menerima kiriman berupa kepala babi dan bangkai tikus.
Peristiwa ini bukan sekadar kasus kriminal biasa, melainkan sebuah serangan terhadap salah satu pilar demokrasi kita: kebebasan pers.
Sebagai akademisi dalam bidang ilmu komunikasi dan jurnalistik, serta sebagai bagian dari Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI), saya memandang peristiwa ini sebagai momentum untuk merefleksikan kembali pentingnya menjaga kebebasan pers di Indonesia.
Pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor Tempo merupakan bentuk kekerasan simbolik yang sangat jelas.
Dalam perspektif teori komunikasi, khususnya dalam pandangan Pierre Bourdieu, kekerasan simbolik merupakan bentuk dominasi yang dilakukan secara halus namun memiliki dampak yang sangat nyata.
Meskipun tidak ada kekerasan fisik yang langsung terjadi, pesan intimidatif yang terkandung di dalamnya justru bisa lebih merusak karena menargetkan aspek psikologis dan sosial dari institusi pers.
Pesan simbolik yang dikirimkan melalui benda-benda menjijikkan tersebut jelas bermaksud untuk menimbulkan rasa takut, jijik, dan tidak aman di lingkungan redaksi.
Dalam analisis framing, tindakan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk membingkai aktivitas jurnalistik sebagai sesuatu yang "kotor" atau "haram" yang pantas mendapatkan balasan serupa.
Ini adalah upaya delegitimasi terhadap kerja-kerja jurnalistik yang sesungguhnya dijamin dan dilindungi oleh konstitusi.
Seperti yang dinyatakan dalam pernyataan pers ISKI Pusat No.: 02/ISKI-PUSAT/III/2025: "Pengiriman pesan berupa bangkai binatang ke kantor redaksi Tempo, merupakan tindakan intimidatif dan teror yang nyata-nyata merendahkan nilai-nilai kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945." Perspektif ini sangat tepat karena bentuk-bentuk intimidasi seperti ini, jika dibiarkan, dapat menimbulkan efek pendinginan (chilling effect) dalam dunia jurnalistik Indonesia.
Konsep "efek pendinginan" (chilling effect) dalam studi jurnalistik merujuk pada situasi di mana jurnalis menjadi ragu-ragu, takut, atau menghindar untuk memberitakan isu-isu sensitif atau melakukan investigasi mendalam karena takut akan konsekuensi negatif yang mungkin mereka terima.
Inilah yang menjadi bahaya terbesar dari intimidasi simbolik seperti yang dialami Tempo.
Ketika jurnalis atau media bekerja dalam iklim ketakutan, fungsi pers sebagai watchdog demokrasi akan melemah.
Jurnalis mungkin akan melakukan self-censorship, menghindari topik-topik kontroversial, atau bahkan mengabaikan informasi penting yang seharusnya diketahui publik.
Pada akhirnya, masyarakatlah yang dirugikan karena kehilangan akses terhadap informasi yang kritis dan berimbang.
Dalam konteks teori ruang publik (public sphere) yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas, pers memiliki peran vital dalam menciptakan dan memelihara ruang diskusi publik yang sehat.
Ketika ruang ini terancam oleh intimidasi, maka demokrasi deliberatif yang menjadi cita-cita masyarakat demokratis akan sulit terwujud.
Oleh karena itu, serangan terhadap Tempo harus dilihat sebagai serangan terhadap ruang publik Indonesia secara keseluruhan.
ISKI Pusat dengan tegas menyatakan: "Pers dalam menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol sosial dijamin oleh undang undang, sehingga pengiriman pesan berupa kekerasan simbolik yang dilakukan secara anonim ke kantor Tempo dapat dimaknai sebagai ancaman serius terhadap kebebasan pers di Indonesia." Pernyataan ini menegaskan bahwa intimidasi terhadap pers bukan sekadar masalah satu institusi media, melainkan menyangkut eksistensi kontrol sosial dalam tatanan demokrasi kita.
Kebebasan Pers sebagai Hak Konstitusional
Kebebasan pers di Indonesia bukanlah pemberian, melainkan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28F yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Selain itu, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers secara spesifik memberikan jaminan kebebasan bagi pers dalam menjalankan fungsinya. Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa "Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara."
Selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa "Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran."
Seperti ditegaskan dalam pernyataan ISKI Pusat: "Pers yang bebas merupakan hasil perjuangan Reformasi 1998, dan oleh karena itu harus tetap dipelihara. Pers tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pihak-pihak tertentu untuk alasan apapun juga." Ini mengingatkan kita bahwa kebebasan pers yang kita nikmati saat ini adalah buah dari perjuangan reformasi yang harus terus dijaga bersama.
Dalam ekosistem demokrasi yang sehat, kritik dan ketidaksepakatan terhadap konten media adalah hal yang normal dan bahkan diharapkan. Namun, penting untuk memahami bahwa terdapat mekanisme yang tepat dan bermartabat untuk menyampaikan kritik atau keberatan tersebut.
ISKI Pusat dengan bijak menyatakan: "Pengurus Pusat ISKI berpendapat, bila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers, maka penyelesaian secara bermartabat merupakan langkah elegan yang dapat ditempuh melalui Dewan Pers, dan atau langkah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah dilakukan oleh sejumlah tokoh nasional."
Dalam kerangka teoritis resolusi konflik media, terdapat beberapa pendekatan yang dapat ditempuh. Pertama, UU Pers memberikan hak jawab dan hak koreksi kepada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan.
Melalui mekanisme ini, pihak tersebut dapat menyampaikan versi atau sudut pandangnya sendiri.
Kedua, Dewan Pers dapat bertindak sebagai mediator dalam sengketa antara media dengan pihak yang merasa dirugikan.
Selain itu, beberapa media memiliki ombudsman internal yang dapat menerima keluhan dari publik.
Sebagai langkah terakhir, jalur hukum dapat ditempuh sesuai dengan prinsip due process of law.
Semua mekanisme di atas jauh lebih bermartabat dan konstruktif dibandingkan dengan aksi intimidasi atau teror yang justru merusak iklim demokrasi.
Media Literacy dan Tanggung Jawab Publik
Di era informasi saat ini, media literacy (literasi media) menjadi keterampilan yang sangat penting bagi masyarakat. Literasi media tidak hanya mencakup kemampuan untuk mengakses dan memahami konten media, tetapi juga kemampuan untuk menganalisis secara kritis, mengevaluasi, dan bertindak secara bertanggung jawab terhadap konten tersebut.
Publik yang memiliki literasi media yang baik akan mampu membedakan antara fakta dan opini dalam pemberitaan, memahami proses produksi berita dan tekanan yang dihadapi jurnalis, mengenali bias dalam pemberitaan dan mencari sumber informasi alternatif, serta menyampaikan kritik secara konstruktif, bukan destruktif.
Dengan meningkatnya literasi media, diharapkan konflik antara media dengan publik atau kelompok kepentingan dapat diselesaikan dengan cara yang lebih bermartabat, tanpa harus mengorbankan kebebasan pers atau menciptakan atmosfer ketakutan bagi jurnalis.
Sebagai bagian dari komunitas akademik dan profesional komunikasi, ISKI telah menunjukkan solidaritas yang kuat terhadap Tempo dan kebebasan pers secara umum. Dalam pernyataan resminya, ISKI dengan tegas menyatakan: "ISKI mendukung pihak Tempo yang telah melaporkan masalah tersebut ke Kepolisian RI dan berharap pelaku kekerasan simbolik tersebut dapat ditemukan untuk dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya."
Solidaritas semacam ini sangat penting karena menciptakan jejaring dukungan yang memperkuat posisi media dalam menghadapi intimidasi.
Dalam perspektif teori modal sosial, dukungan dari organisasi-organisasi seperti ISKI memberikan legitimasi dan sumber daya intangible yang membantu media untuk tetap tegar dalam menjalankan fungsinya.
Selain itu, pernyataan ISKI juga menunjukkan pentingnya penegakan hukum dalam kasus-kasus intimidasi terhadap pers. Hanya dengan penegakan hukum yang konsisten dan tegas, kebebasan pers dapat terjaga dengan baik.
Intimidasi terhadap Tempo harus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kebebasan pers adalah aset berharga yang harus terus dijaga.
Sebagai masyarakat demokratis, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa pers dapat menjalankan fungsinya tanpa rasa takut atau tekanan.
Seperti disampaikan dalam pernyataan ISKI: "Kepada seluruh komponen Pers Nasional, Pengurus Pusat ISKI menyampaikan dukungan sepenuhnya untuk tetap tegar dalam perjuangan membela dan menegakkan kemerdekaan pers yang dijamin konstitusi." Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa perjuangan untuk kebebasan pers adalah perjuangan bersama yang melibatkan tidak hanya jurnalis dan pekerja media, tetapi juga akademisi, profesional komunikasi, dan masyarakat sipil secara luas.
Kita harus ingat bahwa api kebebasan pers yang menyala adalah hasil dari perjuangan panjang reformasi. Api ini tidak boleh padam hanya karena intimidasi atau tekanan dari pihak-pihak yang merasa terganggu dengan fungsi pers sebagai watchdog demokrasi.
Sebagai bagian dari masyarakat demokratis, kita semua memiliki kewajiban untuk menjaga agar api ini tetap menyala terang, menerangi jalan Indonesia menuju demokrasi yang lebih matang dan bermartabat.






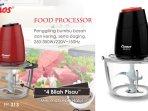











Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.