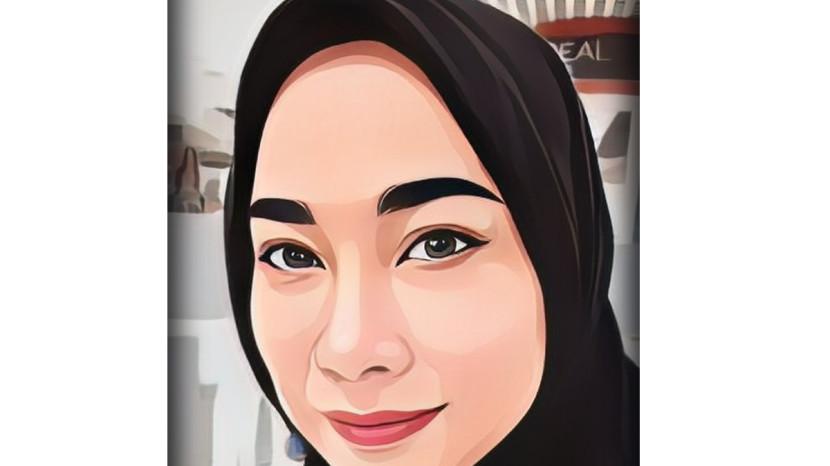Opini Rifqy Tenribali Eshanasir
Mewaspadai Ketegangan di Selat Taiwan
China senantiasa menganggap Taiwan sebagai bagian integral wilayahnya, meskipun wilayah pulau itu memiliki pemerintahan secara mandiri sejak 1949.
Oleh: Rifqy Tenribali Eshanasir
Peneliti di Centre for Peeace, Conflict and Democracy, Unhas
TRIBUN-TIMUR.COM - Sulit dipungkiri bahwa kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat (AS), Nancy Pelosi, ke Taiwan baru-baru ini telah semakin meningkatkan ketegangan di Selat Taiwan, bahkan di Laut China Timur dan kawasan Asia Timur secara umum.
Kunjungan Pelosi memang segera ditanggapi keras pihak China.
Tak menunggu lama setelah kunjungan tersebut, China mengirim pesan tegas berupa pengerahan latihan militer gabungan di Selat Taiwan, termasuk penembakan rudal-rudal konvensional jarak jauh sepert rudal balistik di perairan Taiwan.
Latihan militer di atas termasuk praktis memblokade Taiwan.
China senantiasa menganggap Taiwan sebagai bagian integral wilayahnya, meskipun wilayah pulau itu memiliki pemerintahan secara mandiri sejak 1949.
Pada tahun tersebut, pemimpin komunis Mao Ze-dong menguasai Beijing dan seluruh China daratan setelah mengalahkan pemimpin Kuomintang (Nasionalis) Chiang Kai Shek yang menyingkir dan mendirikan pemerintahan Taiwan.
Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, secara lantang memperingatkan pihak AS bahwa negeri mereka telah melanggar kedaulatan China dengan alasan demokrasi.
Pelosi memang menyebut kunjungannya ke Taiwan sebagai tanda dukungan pada demokrasi, termasuk demokrasi di Taiwan.
Hingga tulisan ini dibuat, pihak AS memang belum menanggapi manuver China berupa latihan militer di atas, namun sebagaimana luas diketahui pihak AS memiliki pangkalan dan asset militer kuat di kawasan tersebut, termasuk kapal induk, yang bisa dikerahkan
setiap saat.
Deeskalasi Konflik
Sebenarnya sejumlah kalangan sudah berusaha memberi peringatan bagi Pelosi untuk mengurungkan kunjungan ke Taiwan, namun kunjungan tersebut tetap terjadi juga.
Dalam kondisi seperti saat ini ketika ketegangan makin meningkat maka yang sangat perlu dilakukan adalah penurunan suhu ketegangan (deeskalasi konflik). Deeskalasi sangat perlu didorong oleh semua pihak untuk mencegah peluang terjadinya konflik terbuka atau perang yang kita tahu akan merugikan semua kalangan.
Sejumlah negara dan organisasi telah menyerukan pentingnya deeskalasi konflik tersebut. Pada hari kedua pertemuan antara kelima menteri luar negeri (menlu) Perhimpuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Phnom Penn, Kamboja, misalnya, para menlu menyatakan perlunya mewaspadai persaingan negara-negara besar, terutama AS dan China di kawasan Asia Tenggara maupun Asia Timur.
Tanpa menyebut eksplisit ketegangan di Selat Taiwan, para menlu ASEAN menyatakan bahwa persaingan negara-negara adidaya di kawasan Asia Pasifik harus dikelola supaya tidak semakin memanas dan meletup menjadi konflik terbuka seperti yang terjadi di Eropa Timur (Perang Rusia-Ukraina), perang yang telah sangat mengganggu rantai pasok pangan dan energi di dunia.
Peran Indonesia dan ASEAN
Indonesia dan ASEAN mesti cermat memposisikan diri di tengah ketegangan yang kian meningkat antara AS dan China di kawasan Asia Pasifik.
Peran Indonesia sebagai kekuatan menengah (middle power) dan pemimpim de-facto ASEAN menjadi strategis. Tentu saja ekspektasi mesti dimoderasi. Tidak mungkin Indonesia dan ASEAN bisa secara langsung menekan China atau AS.
Namun Indonesia dan ASEAN bisa berperan mengurangi ketegangan (deeskalasi) dengan memposisikan diri tidak memihak pada salah satu negara adidaya tersebut.
Cetak biru diplomasi dan politik luar negeri Indonesia, yakni politik luar negeri bebas aktif,adalah panduan utama di tengah memanasnya persaingan AS-China di kawasan Indo-Pasifik.
Pesan salah satu Bapak Bangsa yaitu Bung Hatta ketika perang dingin masih terjadi beberapa dekade lalu juga relevan, yaitu perlunya Indonesia mendayung di antara dua karang, atau menjaga keseimbangan di tengah persaingan kepentingan negara-negara adidaya.
Indonesia dan ASEAN juga dapat berkontribusi dengan makin lantang mendorong pendekatan multilateralisme dalam pengelolaan konflik di kawasan.
Penguaran multilateralisme ini telah disampaikan banyak diplomat dan akademisi hubungan internasional, hukum internasional dan politik luar negeri. Hal ini memang bukan hal mudah untuk diwujudkan.
Namun juga bukan mustahil bila dilakukan secara lebih terkordinir misalnya dengan komunikasi lebih baik antara negara-negara berkembang dan kekuatan menegah (middle power) seperti Indonesia, India, Brazil, Argentian, Afrika Selaran, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam dan sebagainya.
Selain negara-negara, organisasi-organsiasi di tingkat kawasan seperti ASEAN berperan kunci pula dalam mendorong perlunya penguatan multilateralisme, termasuk memperkuatnya dengan basis hukum-hukum internasional yang ada.
Selama ini upaya pengelolaan konflik ataupun deeskalasi ketegangan di kasawan ini lebih banyak dilakukan secara unilateral dan telah terbukti tidak menunjukkan banyak keberhasilan atau kemajuan.
Dalam konteks pesaingan AS dan China yang kian panas di kawasan Indo-Pasifik, peran strategis sentralitas ASEAN dan juga Indonesia yang akan mendapatkan giliran sebagai ketua organisasi ASEAN tahun depan (2023) menjadi semakin penting.
Komunikasi dan kordinasi antara negara ASEAN serta negara-negara lain yang berkepentingan menjaga perdamaian atau menurunkan ketegangan di kawasan sangat vital sehingga eskalasi konflik dapat dicegah dan kesepahaman atau kompromi bisa secara bertahap dicapai. (*)