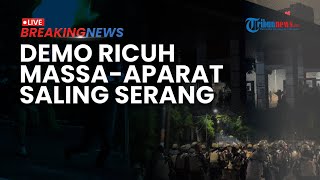Tribun Wiki
9 Wilayah Adat di Seko Luwu Utara, Dipimpin Tobara, Tokei, dan Tomakaka
9 Wilayah Adat di Seko Kabupaten Luwu Utara, Dipimpin Tobara, Tokei, dan Tomakaka
Penulis: Chalik Mawardi | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUNLUTRA.COM, SEKO - Seko merupakan kecamatan di wilayah pegunungan Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.
Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Seko masih terikat kuat dengan nilai-nilai adat yang mereka anut.
Tatanan hidup tidak hanya diatur oleh struktur pemerintahan formal, tetapi juga agama (Kristen), dan norma-norma adat yang masih sangat kuat dijalankan di bawah koordinasi para pemimpin adat.
Secara karakteristik adat istiadat dan geografi, wilayah Seko terbagi atas 3 wilayah adat besar, yaitu Seko Padang, Seko Tengah, dan Seko Lemo.
Seperti yang dijelaskan pada buku Rumah Peradaban Seko dan Rampi diterbitkan Balai Arkeologi Sulawesi Selatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dikutip TribunLutra.com, Senin (31/5/2021).
Lanskap Seko berupa lembah dan perbukitan yang berpadu dengan beberapa aliran sungai yang membelah antara bukit.
Hal ini menjadikan Seko memiliki tanah yang subur yang kemudian dimanfaatkan sebagai areal persawahan yang dikelola oleh masyarakat secara alami.
Selain persawahan, areal padang di Seko dimanfaatkan masyarakat untuk pengembalaan kerbau yang juga menjadi daya tarik tersendiri Seko.
Secara tradisional atau cakupan adat yang lebih kecil (tidak mengikuti batas-batas geografi desa), masyarakat Seko mengakui 9 wilayah adat.
Masing-masing dipimpin oleh Pemuka/Pemimpin Dewan Adat yang menyandang gelar yang berbeda sebagai berikut:
1. Wilayah Adat Lodang dipimpin oleh Tobara’
2. Wilayah Adat Turong dipimpin oleh Tobara’
3. Wilayah Adat Hono dipimpin oleh Tobara’
4. Wilayah Adat Singkalong dipimpin oleh Tokei
5. Wilayah Adat Pohoneang dipimpin oleh Tobara’
6. Wilayah Adat Amballong dipimpin oleh Tobara’
7. Wilayah Adat Hoyane dipimpin oleh Tobara’
8. Wilayah Adat Kariango dipimpin oleh Tomakaka
9. Wilayah Adat Beroppa dipimpin oleh Tomakaka.
Seko adalah nama baru. Awalnya orang-orang yang menghuni tempat ini menamakan diri mereka berdasarkan nama kampung masing-masing.
Hoyane, Eno atau Hono, Lodang, Amballong, atau pula Kariango.
Nama Seko hadir belakangan. Dalam tradisi lisan mereka Seko berarti sahabat, handai tolan, atau kerabat.
Nama ini dicuplik dari perkataan Datu Luwu yang konon bingung menamai orang-orang pegunungan yang saat ini termasuk ke dalam wilayah Seko.
“Jadi Datu Luwu bilang, sahabat itu dalam bahasa di atas (gunung) apa?” ungkap seorang warga. “Itulah Seko.”
Maka sejak saat itu, wilayah yang ditaklukkan Luwu untuk kepentingan hasil bumi itu menjadi Seko.
To Seko (orang Seko). Inilah Seko, tempat damai yang gemuruhnya diluar dicitrakan sebagai tempat terisolir.
Tempat dengan segala macam misteri dan mitos.
Berbeda dengan wilayah atau suku lain di Sulawesi Selatan yang mengenal konsep To Manurung sebagai asal-usul mereka, di Seko, tak ada kisah To Manurung.
Tak ada kisah seorang manusia (To Manurung) yang muncul secara tiba-tiba dan tak seorang pun yang mampu mengurai silsilah leluhur.
Di Seko, orang-orang pertama yang menghuni kampung mampu menelisik urutan garis keturunannya.
Terdapat tiga babakan kisah awal mula orang Seko.
Pertama adalah seorang Matua (orang tua) berjalan dari wilayah Mamasa Sulawesi Barat.
Alkisahnya orang itu meninggalkan kampung karena terjadi peperangan bersama para pengikutnya berjalan hingga ke gunung Sandapang di Kalumpang (Sulawesi Barat).
Orang Tua ini kemudian terus berjalan hingga membawa empat orang anaknya, dan bermukim di wilayah Seko Padang.
Empat anak itu masing-masing; Tabalong yang menjadi kampung Amballong.
Tahayane yang kemudian mendiami kampung Hoyane. Kemudian Tahaneang seorang anak perempuan yang menghuni kampung Pohoneang.
Lalu seorang Tampak yang menghuni Seko Padang wilayah Eno.
Untuk kisah Tampak, dia adalah anak yang senang berburu.
Suatu hari Bersama anjingnya, dia duduk memandangi kawasan lembah Seko Padang-pada mulanya adalah danau.
Anjingnya tiba-tiba bergerak dengan lincah dan memburu seekor rusa.
Tak disangka, rusa itu terjatuh dalam sebuah kolam dan kemudian si anjing ikut turun ke kolam.
Akhirnya, Tampak melakukan mudihata (semedi).
Dia memanggil kepiting, belut dan beberapa hewan air lainnya, untuk membuka tamolang (saluran air).
Kolam itu akhirnya menjadi kering, dan menjadi daratan.
Anjing itu terus berusaha memburu rusa. Tampak mengikutinya dan sampai di wilayah yang bernama Taloto – dalam bahasa lain Talotong atau orang yang lidahnya hitam.
Di wilayah ini, Tampak tak menemukan anjingnya lagi. Dia kemudian membuat kolam untuk memelihara ikan. Tapi kemudian air kolam tersebut selalu keruh.
Kolam itu akhirnya dikenal dengan nama Mabubu hingga sekarang masih ada dan dimiliki seseorang.
Kekeruhan kolam itu, akhirnya diketahui Tampak karena ulah beberapa dayang (dewi) yang selalu datang mandi.
Baju salah satunya, dicuri - seperti kisah Jaka Tarub di Jawa – Tampak menikahi salah seorang dewi itu. Tampak dan sang dewi melahirkan dua orang anak.
Mereka bertumbuh dan besar, dan kemudian menyebar di seantero Seko. Sang Dewi, kemudian meninggalkan Tampak melalui longa (jendela di bagian bawah atap rumah adat) ketika melanggar perjanjian karena dalam kemarahan pada anaknya, menyebutkan jika sang istri adalah mahluk halus.
Sementara versi yang paling tenar adalah kedatangan Ulu Pala. Seorang dengan tangan yang berbulu. Dia berasal dari Kanandede, wilayah dekat Rongkong.
Ulu Pala diasuh seorang pasangan suami istri. Pada suatu ketika, orang tua angkat Ulu Pala yang berhutang pada orang Toraja mendatanginya.
Ulu Pala menaklukkan penagih hutang itu dengan teka teki. Setelah itu, orang Toraja menyebar fitnah jika Ulu Pala adalah seorang anak yang tak bisa membawa keberuntungan.
Orang tua Ulu Pala termakan hasutan tapi memilih tak membunuhnya. Dia kemudian membawa Ulu Pala dan diasingkan ke wilayah yang sekarang masuk Seko Tengah.
Ulu Pala yang kesepian membuat gambar di sebuah batu, yang saat ini dikenal sebagai Hatu Rondo.
Dan akhirnya seorang dewi mendatanginya lalu mereka menikah dan bermukim di kampung tua bernama Bongko.
Toponim Bongko saat ini masuk dalam wilayah Dusun Kampung Baru, Desa Padang Balua. Hasil penelitian awal yang dilakukan Balai Arkeologi Sulawesi Selatan pada 2015, di Situs Bongko ditemukan tinggalan arkeologis berupa batu monolith yang kemungkinan berfungsi sebagai umpak-umpak batu.
Batu monolith ini tersebar secara tidak berpola, sebagian besar umpak ini telah rebah dan tertimbun dalam tanah.
Untuk menemukan umpak batu ini sangat sulit, mengingat keletakannya yang saat ini berada dalam hutan yang agak lebat.
Temuan lain adalah fragmen tembikar yang tersebar cukup banyak di permukaan situs.
Hal inilah yang menarik bahwa cerita tutur yang disampaikan oleh Tobara terkait dengan sejarah Seko, dapat dibuktikan secara arkeologis sebagaimana hasil penelitian awal Balai Arkeologi Sulawesi Selatan di Situs Bongko.
Tinggalan arkeologis disana mengindikasikan adanya jejak aktifitas manusia pada masa lalu.
Hal ini tentunya menjadi potensi pengembangan khususnya terkait penelitian arkeologi dan sejarah di Seko.(*)