Opini
Roblox: Gaduh di Tanah Air
Ia disusun dari serpihan peristiwa, dipoles oleh narasi kekuasaan, lalu dipertontonkan seolah kebenaran.
Oleh: Iwan Mazkrib
Ketua Bidang Perlindungan HAM Badko HMI Sulsel
TRIBUN-TIMUR.COM - Sejarah bangsa, pada hakikatnya adalah upaya rekonstruksi yang tak pernah usai.
Ia disusun dari serpihan peristiwa, dipoles oleh narasi kekuasaan, lalu dipertontonkan seolah kebenaran.
Dari revolusi kemerdekaan, reformasi, hingga riuh delapan dekade pasca-proklamasi, sejarah sering kali lebih menyerupai mitologi politik daripada cermin realitas.
Sejarah, kata Hegel, berulang sebagai tragedi, lalu farsa. Dan Indonesia, delapan puluh tahun setelah proklamasi, seakan sedang memainkan keduanya sekaligus.
Demonstrasi besar, penjarahan rumah pejabat dan pasar, pembakaran kantor DPR, pemberangusan fasilitas umum, gesekan SARA yang dipantik, hingga wacana darurat militer, semuanya hadir bagai fragmen yang mengingatkan bahwa negeri ini, yang diperjuangkan dengan darah dan air mata, masih kerap ditarik ke tepi jurang yang sama.
“Revolusi belum selesai,” gema Bung Karno, melintasi zaman. Sayangnya, ia lebih sering dijadikan slogan spanduk ketimbang renungan politik.
Revolusi belum selesai, selama masih ada tangis rakyat yang tercecer di jalanan.
Kita memang merdeka dari kolonialisme asing, tetapi belum merdeka dari kolonialisme baru: kerakusan elite, represivitas aparat, dan ketergantungan rakyat pada rekayasa kepentingan yang dikendalikan segelintir tangan.
Lihatlah berita tanah air: seorang pengemudi ojol remuk di bawah ban Rantis; kampus, rumah ilmu, diserbu aparat seolah pikiran kritis adalah makar, rumah pejabat, pasar, hingga kantor DPR dijarah yang hilang bukan sekadar harta benda, melainkan legitimasi yang telah lama keropos.
Di balik asap ban terbakar, bisikan getir beredar: isu makar, wacana darurat militer, hingga narasi musuh dalam selimut. Semua adalah instrumen retoris untuk menutupi kenyataan telanjang: negara gagal mengelola perbedaan, dan memilih menindasnya.
Kita seperti hidup dalam jagat Roblox: dunia digital tempat bangunan megah runtuh dalam sekejap, lalu dibangun kembali tanpa fondasi. Tetapi Indonesia bukan Roblox. Nyawa tak bisa di-restart, luka tak bisa dihapus dengan tombol delete, dan sejarah tak pernah menyediakan menu reset.
Ironinya, bangsa merayakan era post-trust: rakyat tidak lagi percaya pada janji negara, sementara negara justru mencurigai rakyat sebagai ancaman.
Survei kepercayaan publik terhadap DPR, Polri, dan lembaga negara menunjukkan tren menurun tajam. Namun, yang lebih berbahaya dari grafik adalah fakta bahwa ketidakpercayaan kini telah menjadi identitas politik rakyat.
Tan Malaka pernah menulis dalam Madilog: “Hanya aksi massa yang dapat mengubah roda sejarah.” Tetapi ke arah manakah roda itu digerakkan?
Massa turun ke jalan, namun yang mereka terima hanyalah stigma: perusuh, pengganggu, ancaman. Sementara kriminalisasi dan pelanggaran HAM dinormalisasi, dilapisi jargon “stabilitas nasional” yang retoris, padahal nihil substansi.
Di titik ini, pertanyaan menjadi tak terelakkan. Untuk apa delapan puluh tahun merdeka, bila negara justru menormalisasi pelanggaran HAM? Untuk apa slogan “Indonesia Emas 2045” didengungkan, bila di jalan-jalan masih terdengar jerit mahasiswa dipukul, fasum dibakar, dan kegaduhan ditunggangi oleh kelompok berkepentingan?
Sejarah telah memberi kita pelajaran pahit. Dari DPR yang membisu 1966 memantik gelombang mahasiswa.
Jalanan 1998 meruntuhkan rezim yang dianggap abadi. Kini, gedung DPR kembali terbaka. Bukan hanya fisiknya, tetapi juga nurani yang terkubur bersama legitimasi rakyat. Dan api itu, sekali lagi, merenggut nyawa.
Namun bangsa ini tidak boleh terus-menerus dikurung dalam siklus gaduh. Reaksi bukan solusi. Kita membutuhkan rekonstruksi dengan akal sehat, bukan senjata.
Nasionalisme yang cerdas, bukan yang gaduh. Negara yang hadir sebagai pelindung, bukan algojo.
Di sinilah tugas organ mahasiswa, komunitas sipil, dan lembaga pendidikan. Mereka mesti melampaui romantisme jalanan.
Kritik tetap penting, tetapi harus dilengkapi riset, karya, dan kebijakan alternatif. SDM yang tangguh adalah satu-satunya benteng bangsa dalam dunia global yang kian cair.
Nasionalisme hari ini bukan lagi sekadar menyanyikan lagu perjuangan, tetapi merumuskan solusi, teknologi, dan ide yang menyejahterakan rakyat.
Refleksi ini hanya dapat bermuara pada dogma solutif:
* Pemerintah wajib berpihak pada rakyat, bukan oligarki.
* Reformasi Polri dan DPR adalah urgensi historis, bukan jargon. Aparat harus kembali ke khitah: melindungi, bukan menindas. DPR harus kembali menjadi lidah rakyat, bukan corong kuasa.
* Organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil harus menjelma laboratorium gagasan. Tidak cukup jadi pengeras suara, mereka mesti jadi pencerah bangsa.
* Trust antara negara dan rakyat harus dipulihkan, sebab tanpa itu, “Indonesia Emas” hanya akan jadi dongeng korporatis yang usang.
Pada akhirnya, gaduh bukanlah takdir bangsa, melainkan pilihan elite yang gagal mengelola perbedaan.
Pramoedya Ananta Toer pernah mengingatkan: “Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan.”















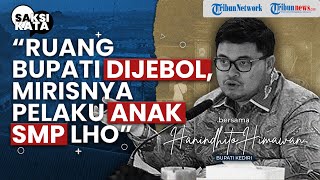






Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.