Opini
Kerentanan Saling Mengunci di Pesisir: Kemiskinan Struktural dan Perubahan Iklim
Di wilayah seperti Kepulauan Spermonde, nelayan skala kecil menghadapi badai yang tak sekadar datang dari laut.
Oleh: Prof Dr Andi Adri Arief SPi MSi
Guru Besar Sosiologi Perikanan Universitas Hasanuddin
TRIBUN-TIMUR.COM - Krisis iklim menjelma menjadi palung krisis yang menghisap segala kepastian hidup masyarakat pesisir.
Di wilayah seperti Kepulauan Spermonde, nelayan skala kecil menghadapi badai yang tak sekadar datang dari laut, tapi juga dari struktur sosial yang timpang: fluktuasi hasil tangkap, pergeseran fishing ground, gelombang ekstrem, dan hilangnya musim sebagai penanda ritme ekonomi.
Data terbaru menunjukkan 79,5 persen rumah tangga nelayan di empat pulau Spermonde (Pulau Barrang Lompo dan Pulau Badi, Pulau Kodingareng Lompo dan Pulau Ballang Lompo) berada pada tingkat kerentanan ekonomi yang sangat tinggi akibat kombinasi abrasi pantai, kenaikan suhu laut, dan penurunan hasil tangkapan ikan (Idrus et al, 2024)
Fenomena pemutihan terumbu karang (bleaching) juga telah menyebabkan berkurangnya habitat ikan yang memaksa nelayan melaut lebih jauh dari sebelumnya hingga meningkatkan biaya dan risiko operasional. Sulitnya memprediksi musim—hujan atau kemarau—menambah ketidakpastian lingkungan sehingga nelayan sulit merencanakan kapan harus melaut.
Habitus yang Tercekik: Ketika Tradisi Tidak Lagi Menyelamatkan
Pierre Bourdieu mengajarkan bahwa tindakan sosial dibentuk oleh habitus—disposisi yang tertanam melalui sejarah.
Melaut, dalam konteks masyarakat pesisir, bukan hanya kegiatan ekonomi, melainkan ekspresi identitas sosial yang diwariskan.
Namun dalam arena yang berubah oleh krisis iklim dan liberalisasi ekonomi, habitus nelayan menjadi tidak cukup.
Ia justru berubah menjadi beban ketika tak ada jembatan ke arena baru yang menuntut literasi teknologi, diversifikasi ekonomi, dan relasi pasar modern.
Masyarakat pesisir terperangkap dalam keterputusan sejarah: di masa lalu, mereka digdaya di laut; di masa kini, mereka kehilangan tempat berpijak.
Dan negara, yang seharusnya menjadi penyeimbang struktur, justru hadir dalam bentuk proyek: alat tangkap, pelatihan singkat, dan angka statistik tanpa jiwa.
Dialektika Struktural Giddens: Ketika Agensi Dibiarkan Rapuh
Dalam teori strukturasi Anthony Giddens, struktur tidak deterministik; ia memungkinkan agensi.
Tapi dalam realitas masyarakat pesisir, agensi itu tidak cukup diberi ruang.
Negara menciptakan struktur kebijakan yang tidak akomodatif terhadap kondisi sosial rumah tangga nelayan: dari bantuan yang tersentralisasi, distribusi alat tangkap yang tidak merata, hingga absennya sistem perlindungan sosial berkelanjutan.
Maka, agensi rumah tangga pesisir menyempit. Diversifikasi penghasilan hanya mungkin dilakukan oleh sekitar 20 persen keluarga.
Sisanya bertahan dalam pilihan yang bukan pilihan. Mereka bertahan bukan karena punya daya, tetapi karena tidak punya tempat mundur.
Data nasional memperkuat hal ini: studi pemetaan kerentanan di Aceh Selatan, Pemalang, Pangkep, dan Ambon oleh KNTI–EcoNusa–UI menemukan bahwa rata-rata 51 persen responden menghadapi kerentanan akibat perubahan iklim, dan 29 % mengalami gangguan akses BBM, sedangkan 20 % menghadapi ketidakpastian wilayah tangkap.
Dalam konteks ini, teori adaptasi seperti yang digambarkan Smit dan Wandel menjadi penting: adaptasi bukan hanya reaksi, melainkan kapasitas sosial untuk bertahan dan mentransformasi kondisi struktural yang menindas.
Sayangnya, kemampuan adaptif masyarakat pesisir—yang seharusnya menjadi pengungkit agensi—justru dipinggirkan oleh absennya dukungan sistemik dan kebijakan yang dialogis.
Kerentanan ini membuat nelayan terpaksa membangun strategi spontan: berpindah daerah tangkap, diversifikasi pekerjaan ke sektor informal, hingga mengandalkan mobilisasi keluarga.
Namun tanpa dukungan negara, strategi ini hanyalah bentuk “survivalisme yang melelahkan”, bukan jalan keluar struktural.
Perempuan Pesisir: Pilar yang Dilupakan
Dalam diam, perempuan pesisir menjadi agen adaptasi utama, bahkan ketika negara tak melihat mereka.
Mereka mengatur keuangan rumah tangga yang semakin keropos, membentuk jaringan arisan dan gotong royong, menjahit, menjual kue, meminjam ke warung, atau menjual barang rumah tangga.
Mereka menyerap kerentanan di ruang-ruang domestik, dengan logika ketahanan yang tak tercatat dalam indikator pembangunan. Dalam perspektif feminis, ini adalah bentuk dari “kerja ganda” sekaligus “kerja tak terlihat” (invisible labor) yang menopang keberlanjutan rumah tangga.
Di tengah kerentanan, mereka tidak hanya mengelola konsumsi dan utang, tetapi juga menjaga kohesi sosial komunitas—melalui jaringan pengasuhan kolektif, komunitas keagamaan, hingga solidaritas informal.
Justru dari dapur dan teras rumah, perempuan pesisir menjalankan perlawanan terhadap perubahan iklim dengan cara mereka sendiri—diam, namun tak kalah kuat dari gelombang.
Agensi Kolektif: Jaringan Sosial sebagai Perisai Terakhir
Dalam situasi di mana negara absen, komunitas menciptakan strategi bertahan kolektif: barter, gotong royong, saling utang tanpa bunga, hingga koperasi kecil berbasis kepercayaan.
Ini adalah bentuk modal sosial (social capital) yang menjadi jangkar dalam laut yang bergelora. Tapi tanpa dukungan struktural, kekuatan ini bisa berubah menjadi beban yang melelahkan secara sosial (social exhaustion).
Kemandirian ini, sebagaimana dijelaskan Arief, A.A (2021), berakar pada jaringan sosial vertikal dan horizontal—relasi patron-klien dengan punggawa/pappalele/bos, dan solidaritas antar tetangga.
Namun struktur ini tidak bebas dari reproduksi ketimpangan. Dalam situasi paceklik, akses terhadap sumber daya justru dikendalikan oleh segelintir aktor modal.
Maka, bentuk infrapolitik yang dijelaskan James Scott (1990) menjadi ambivalen: antara strategi perlawanan dan sekaligus bentuk kooptasi sosial yang menjebak komunitas dalam jebakan adaptasi paksa.
James Scott menyebut ini sebagai bentuk infrapolitik—perlawanan yang tersembunyi, tapi terus berlangsung.
Maka kita harus bertanya: mengapa strategi bertahan itu terus dibebankan kepada masyarakat, sementara struktur dominan tidak bergerak?
Rekomendasi: Dari Ketahanan ke Keadilan Sosial-Ekologis
Pergeseran pendekatan dari sekadar “ketahanan” menuju “keadilan sosial-ekologis” menuntut perubahan cara pandang negara terhadap rumah tangga pesisir.
Adaptasi terhadap perubahan iklim harus dimulai dari rumah tangga, bukan dari komoditas. Rumah tangga nelayan perlu
dipahami sebagai satuan sosial-ekologis yang kompleks, bukan hanya sasaran program teknis yang seragam.
Negara harus hadir secara substansial dalam membangun ekosistem diversifikasi penghasilan—bukan hanya dengan pelatihan sesaat, tetapi dengan jaminan akses terhadap modal, pasar, dan pendampingan jangka panjang.
Dalam proses itu, penguatan peran perempuan menjadi kunci. Kebijakan afirmatif seperti pengembangan koperasi perempuan, asuransi informal, serta pengakuan kerja domestik sebagai kontribusi ekonomi harus diwujudkan sebagai bentuk keadilan gender dalam kebijakan iklim.
Tak kalah penting, forum adaptasi berbasis komunitas perlu dibangun agar pengetahuan lokal masyarakat pesisir dapat berjalan berdampingan dengan hasil-hasil riset ilmiah—membentuk pengetahuan hibrid yang kontekstual dan responsif.
Pendidikan juga harus menjadi alat mobilitas sosial generasi muda pesisir.
Beasiswa afirmatif, sekolah kontekstual (Sekolah Rakyat) yang menyatu dengan ekosistem pesisir, serta pelatihan vokasional berbasis lokal harus menjadi prioritas.
Lebih jauh lagi, strategi adaptasi tidak boleh mengabaikan dimensi pengetahuan dan ketahanan kolektif.
Mengintegrasikan riset ilmiah dengan pengetahuan lokal serta membangun institusi yang mampu meningkatkan kapasitas sosial rumah tangga adalah langkah tak terelakkan.
Hal ini mencakup pelatihan teknologi penangkapan ramah lingkungan dan jaminan sosial berbasis risiko iklim, sehingga masyarakat pesisir tidak hanya diminta bertahan—tetapi mampu merancang masa depan mereka sendiri secara bermartabat.
Menghadapi Dua Kerentanan yang Saling Mengunci
Ketika dua kerentantan besar—kemiskinan struktural dan perubahan iklim—bertemu di ruang hidup masyarakat pesisir, maka yang terjadi bukan sekadar penderitaan ganda, tetapi krisis yang saling memperdalam dan mempercepat keterpurukan.
Kemiskinan struktural yang telah lama membelenggu rumah tangga pesisir membuat mereka tidak memiliki cadangan sosial maupun ekonomi untuk menghadapi perubahan iklim yang semakin tidak terprediksi.
Sementara itu, dampak iklim yang ekstrem, seperti gelombang tinggi, cuaca tak menentu, dan rusaknya ekosistem laut, semakin mempersempit pilihan hidup mereka.
Dalam kondisi demikian, rumah tangga pesisir menghadapi bahaya ganda: kerentanan ekonomi yang membuat mereka bergantung pada satu sumber penghidupan, dan kerentanan ekologis yang membuat sumber itu semakin rapuh.
Tanpa intervensi struktural, keduanya akan terus saling mengunci, membuat keluar dari lingkaran kemiskinan menjadi nyaris mustahil.
Karena itu, solusi tidak bisa lagi bersifat sektoral dan teknokratis. Diperlukan pendekatan kebijakan yang holistik, berbasis keadilan sosial-ekologis, yang mengakui rumah tangga pesisir bukan hanya sebagai objek bantuan, melainkan sebagai agen sosial yang punya hak atas hidup yang layak.
Penguatan ekonomi lokal, pengakuan atas kerja perempuan, integrasi pengetahuan lokal dan ilmiah, serta pendidikan kontekstual untuk generasi muda adalah jalan untuk membebaskan mereka dari jebakan dua krisis ini.
Sudah waktunya negara tidak lagi menuntut ketahanan dari masyarakat yang telah lama dibiarkan sendiri.
Yang dibutuhkan bukan sekadar bertahan, melainkan tumbuh: menjadi kuat secara sosial, tangguh secara ekologis, dan merdeka secara struktural.(*)






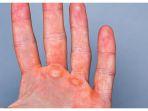












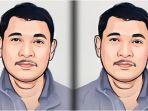


Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.