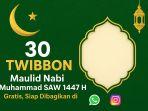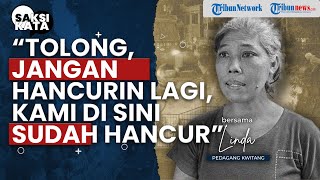Opini Dwi Rezki Hardianto
KKN di Desa Penari sebagai Otoritas Simbolik
Pada awalnya cerita KKN di Desa Penari (kemudian disebut KDDP) adalah kisah horor yang dicitrakan dan disebarluaskan melalui twitter.
Dwi Rezki Hardianto SS MA
Alumnus Magister Sastra FIB UGM
TRIBUN-TIMUR.COM- Pada awalnya cerita KKN di Desa Penari (kemudian disebut KDDP) adalah kisah horor yang dicitrakan dan disebarluaskan melalui twitter mulai pada 24 Juni-25 Juli 2019.
Akun yang menuliskan kisah ini adalah @SimpleM81378523 atau juga disebut Simpleman.
Tidak ada yang mengetahui secara pasti siapa dan dari mana asal Simpleman. Hal ini masih menjadi sebuah teka-teki.
Namun, hal yang menarik adalah kita mengenal penulisnya melalui thread twitter-nya. Dengan demikian pula kita mampu membenamkan diri pada teksnyabukan karena popularitas penulisnya sebagaimana yang terjadi di dalam fenomena sastra saat ini.
Hingga saat ini, KDDP telah melalui tiga ruang produksi sekaligus reproduksi. (1) Ketika KDDP menjadi sastra siber melalui thread twitter, (2) ketika KDDP direproduksi menjadi novel pada September 2019, dan (3) kemudian ditransformasikan menjadi film dan tayang pertama kali pada 30 April 2022.
Sebagai asumsi, salah satu sebab utama KDDP direproduksi hingga menjadi film, yaitu KDDP mampu mengundang atensi dari masyarakat luas melalui komentar-komentar baik dari twitter hingga media sosial lainnya.
Hal ini tentu menjadikan KDDP semakin viral dan populer. Dengan demikian, KDDP dapat disebut pula sebagai sastra populer sehingga kepopuleran inilah yang direproduksi.
Salah satu penelitian yang berasal dari Poetika Jurnal Ilmu Sastra, yaitu Degradasi Puitika dalam Kontestasi Literasi Cerita KKN di Desa Penari (2019) menuturkan bahwa kepopuleran dari sebuah karya dapat disimak dari sisi kuantitas, objektif dan masifnya. Apalagi KDDP masuk ke dalam genre horor.
Kehororan itu terdemonstrasikan dari kehadiran dominasi horor nan mistik dalam teks.
Bukankah mayoritas masyarakat indonesia masih menyukai mistisisme?
Hal itu dibuktikan bahwa penonton film KDDP telah mencapai 5 jutaan pada 14 Mei 2022.
Hal ini tentu menjadi film horor terpopuler yang pernah ada di Indonesia. Namun, selama belum mengalahkan Dilan 1990 (6,3 jutaan) dan Warkop DKI Reborn Jangkrik Boss! Part 1 (6,8 jutaan).
Maka, Ia belum berhasil mengalahkan kegagahan Iqbal (Dilan) dan mengalahkan ketenaran masa lalu Dono, Kasino, dan Indro.
Meskipun demikian, saya berasumsi bahwa keviralan KDDP sebenarnya bukan karena artris di dalamnya, melainkan adanya panggilan-panggilan lain yang (diaggap) mampu menutupi teka-teki (makna) dalam benak masyarakat.
Ruang Antara
KDDP adalah ruang antara yang mampu meleburkan paradigma fiksi dan fakta.
Artinya, dirinya menjadi medan perjumpaan di antara kedua paradigma itu. Setidaknya peleburan itu melalui tiga hal, yaitu refleksi berulang karakter khususnya Nur, Widya dan Ayu, repetisi peristiwa, hingga disnarasi.
Ketiganya tentu menciptakan eventfulness (kepenuh-peristiwaan) yang membuat pembaca terbenam di dalam teks itu sendiri. Hal yang menarik dari ketiga tersebut adalah adanya disnarasi.
Konsep disnarasi adalah strategi penceritaan peristiwa yang sengaja disembunyikan sehingga pembaca mengalami ketidakjelasan atas peristiwa-persitiwa tertentu. Misalnya, ketika anak-anak KKN dilarang keras untuk memasuki “Tipak talas” oleh Pak Prabu.
Namun, pak Prabu enggan menceritakan alasannya lebih jauh. Tujuan dari penangguhan makna itu agar pembaca dapat terlibat penuh menelusuri belantara teks hingga selesai.
Namun, menurut saya juga disnarasi adalah salah satu strategi untuk menjadikan cerita itu tetap hidup, bahkan mampu melampaui imajinasi fiksi itu sendiri. Misalnya disnarasi penokohan hingga setting tempat—Kota J, Kota B, Desa W, Hutan D**** dan lain sebagainya.
Sebelum menjadi film, disnarasi ini tentu menjadi sebuah ruang identifikasi yang diimajinasikan lebih jauh oleh pembaca (audiens) sebagai subjek. Imajinasi itu tentu tersebar di media sosial—dengan beragam asumsi penanda.
Ada yang mengatakan berada di banyuwangi, di jawa tengah dan masih banyak lagi dengan menyamakan penanda-penanda ritus-ritus budaya dalam KDDP.
Selan itu, untuk penokohan ada yang mengatakan ini adalah fakta dengan beredarnya foto-foto lawas mahasiswa KKN dengan lokasi—diasumsikan—sama.
Padahal apa yang ditangkap oleh pembaca (audiens), mungkin saja tidak benar keberadaanya di realitas kita.
Otoritas Simbolik
Saya menggap bahwa KDDP telah menjadi rezim atau otoritas kebahasaan yang mampu mengintervensi dan mengeksklusi imajiner subjek (penonton).
Gagasan tersebut ibarat the name of father atau ayah oedipus dalam paradigma psikoanalisis. Sebenarnya, saya telah mengasumsikan hal tersebut, sejak KDDP menjadi novel apalagi saat dirilis pertama kali untuk menjadi film.
Ketika KDDP ditayangkan ke layar lebar, saya berpikir bahwa apa yang dicitrakannya ibarat otoritas makna yang berusaha mengintervensi imajinasi kita.
Kehadiran beberapa setting tempat dengan jelas dan karakteristik penokohan dalam film menjadi satu makna yang dicitrakan cukup terang—meskipun Widya di akhir film mengatakan “semuanya harus disamarkan”, tetapi pernyataan itu justru menegasikan bahwa KDDP adalah sebuah kenyataan.
Apalagi ketika berita-berita menarasikan setting tempatnya cukup jelas berada di “Jawa Timur” di dalam thread twitter, Simpleman hanya mengatakan “timur jawa” dan bukan berarti di jawa timur.
Menurut saya, hal tersebut mengimplikasikan dua hal: (1) dinarasi sebagai strategi menjadi lenyap untuk membangun keterlibatan penonton sebagai bagian dari lakon, atau (2) malah sebaliknya, subjek penonton—yang belum memiliki pengalaman sebelumnya—akan menjadikannya sebagai ruang identifikasi baru, melalui pembacaan ulang—pada teks-teks sebelumnya—untuk mengungkap kebenaran lain di balik film (citra) tersebut.(*)