TRIBUNWIKI: Cawapres Ma'ruf Amin Klaim Punya Darah Keturunan Prabu Siliwangi, Ini Silsilahnya!
Cawapres nomor urut 02, Maruf Amin yang mengklaim dirinya sebagai turunan Prabu Siliwangi.
Penulis: Desi Triana Aswan | Editor: Anita Kusuma Wardana
Pangeran Walangsungsang sebagai Sultan Cirebon I dan Sunan Gunung Jati sebagai Sultan Cirebon II dalam Kesultanan Cirebon sejak tahun 1430 M.
Setelah terbuka jati diri Sang Prabu Jayadewata masih kerabat, lalu diantarkannya menemui ayah Prabu Amuk Murugul, yaitu Prabu Susuktunggal kakak lain Ibu Prabu Dewa Niskala ayahnya Prabu Jayadewata, di Kerajaan Sunda Bogor sekarang dan dijodohkan dengan Nyai Kentring Manik Mayang Sunda putri Prabu Susuktunggal, yang nanti melahirkan Prabu Sanghyang Surawisesa kelak jadi pengganti Sri Baduga Maharaja di Pakuan Pajajaran dan Sang Surasowan jadi Adipati di Pesisir Banten atau Banten Girang.
Sang Surasowan berputra Adipati Arya Surajaya dan putri Nyai Kawung Anten.
Nyi Kawung Anten kelak menikah dengan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Djati dan melahirkan Pangeran Sabakingkin alias Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten tahun 1552 M.
Prabu Siliwangi juga menikahi Ratu Istri Rajamantri putri Prabu Gajah Agung putra Prabu Tajimalela atau Prabu Agung Resi Cakrabuana putra Prabu Aji Putih atas perintah Prabu Suryadewata putra untuk mendirikan Kerajaan Sumedang larang tahun 900 M.
Nama kerajaannya berubah-ubah, Kerajaan Tembong Agung saat Prabu Aji Putih, zaman Prabu Tajimalela, diganti menjadi Himbar Buana, yang berarti menerangi alam, Prabu Tajimalela pernah berkata Insun medal Insun madangan.
Artinya Aku dilahirkan, Aku menerangi.
Sumedang dan Larang berarti sesuatu yang tidak ada tandingnya.
Ratu Pucuk Umun Sumedang keturunan Prabu Gajah Agung menikah dengan Pangeran Pangeran Kusumahdinata atau Pangeran Santri putra Pangeran Pamelekaran atau Pangeran Muhammad, sahabat Sunan Gunung Jati.
Ibu Pangeran Santri Ratu Martasari/Nyi Mas Ranggawulung, keturunan Sunan Gunung Jati dari Cirebon.
Dari pernikahan itu lahir Prabu Geusan Ulun yang memerintah Sumedang Larang (1578-1610) M bersamaan dengan berakhirnya Pakuan Pajajaran tahun 1579 M, menerima mahkota emas milik Raja Pakuan Pajajaran yang bernama Binokasih (Mahkota Binokasih) dari senapati Pajajaran sebagai tanda bahwa Kerajaan Sumedang Larang penerus sah Kerajaan Pajajaran.
Saat Menjadi Raja
Tindakan pertama yang diambil oleh Sri Baduga setelah resmi dinobatkan jadi raja adalah menunaikan amanat dari kakeknya (Wastu Kancana) yang disampaikan melalui ayahnya (Ningrat Kancana) ketika ia masih menjadi mangkubumi di Kawali.
Isi pesan ini bisa ditemukan pada salah satu prasasti peninggalan Sri Baduga di Kebantenan. Isinya sebagai berikut (artinya saja):
Semoga selamat. Ini tanda peringatan bagi Rahyang Niskala Wastu Kancana.
Turun kepada Rahyang Ningrat Kancana, maka selanjutnya kepada Susuhunan sekarang di Pakuan Pajajaran.
Harus menitipkan ibukota di Jayagiri dan ibukota di Sunda Sembawa.
Semoga ada yang mengurusnya.
Jangan memberatkannya dengan "dasa", "calagra", "kapas timbang", dan "pare dongdang".
Maka diperintahkan kepada para petugas muara agar jangan memungut bea. Karena merekalah yang selalu berbakti dan membaktikan diri kepada ajaran-ajaran.
Merekalah yang tegas mengamalkan peraturan dewa.
Dengan tegas di sini disebut "dayeuhan" (ibukota) di Jayagiri dan Sunda Sembawa.
Penduduk kedua dayeuh ini dibebaskan dari 4 macam pajak, yaitu "dasa" (pajak tenaga perorangan), "calagra" (pajak tenaga kolektif), "kapas timbang" (kapas 10 pikul) dan "pare dondang" (padi 1 gotongan).
Dalam kropak 630, urutan pajak tersebut adalah dasa, calagra, "upeti", "panggeureus reuma".
Dalam akhir abad ke-19 bentuknya berubah menjadi "lakon gawe" dan berlaku untuk tingkat desa.
Karena bersifat pajak, ada sangsi untuk mereka yang melalaikannya.
Dari sinilah orang Sunda mempunyai peribahasa "puraga tamba kadengda" (bekerja sekadar untuk menghindari hukuman atau dendaan).
Bentuk dasa pada dasarnya tetap berlangsung.
Di desa ada kewajiban "gebagan" yaitu bekerja di sawah bengkok dan ti tingkat kabupaten bekerja untuk menggarap tanah para pembesar setempat.
Jadi "gotong royong tradisional berupa bekerja untuk kepentingan umum atas perintah kepala desa", menurut sejarahnya bukanlah gotong royong.
Memang tradisional, tetapi ide dasarnya adalah pajak dalam bentuk tenaga.
Dalam Pustaka Jawadwipa disebut karyabhakti dan sudah dikenal pada masa Tarumanagara dalam abad ke-5.
Piagam-piagam Sri Baduga lainnya berupa "piteket" karena langsung merupakan perintahnya.
Isinya tidak hanya pembebasan pajak tetapi juga penetapan batas-batas "kabuyutan" di Sunda Sembawa dan Gunung Samaya yang dinyatakan sebagai "lurah kwikuan" yang disebut juga desa perdikan, desa bebas pajak.
Ketika memerintah Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin yang menganut gaya kepemimpinan Egalitarianisme.
Egalitarianisme sendiri memiliki arti sebagai paham yang memegang teguh azas kesetaraan dalam kehidupan sosial. hal tersebut sering digambarkan dalam berbagai literasi menenai Prabu Siliwangi.(*)
Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:
Follow juga Instagram Tribun Timur:
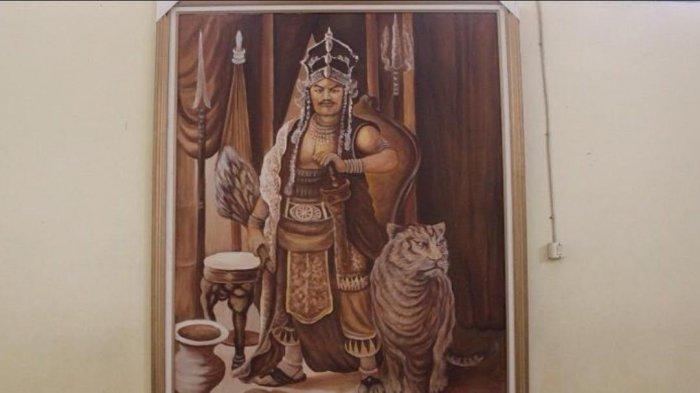
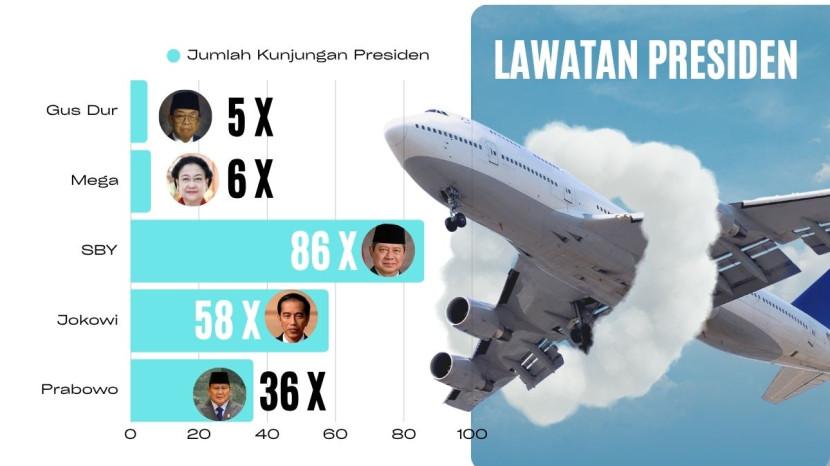







![[FULL] Puja-Puji Trump ke Prabowo, Pakar: Indonesia Ukir Sejarah Jadi Bagian Perdamaian Timur Tengah](https://img.youtube.com/vi/fJn8tji_3J8/mqdefault.jpg)





